Daftar Isi
TogglePertama: dari sisi cakupan kaidah dan luasnya jangkauan terhadap cabang-cabang dan permasalahan fikihTingkatan pertama: Kaidah kubra yang cakupan kaidahnya luas dan menyeluruh terhadap cabang dan permasalahan fikihTingkatan kedua: Kaidah-kaidah yang cakupannya lebih sempit daripada kaidah-kaidah sebelumnya (meskipun tetap bersifat luas dan mencakup banyak hal); di bawah setiap kaidah tersebut terdapat banyak sekali permasalahan fikih yang tidak terhitung jumlahnyaBagian pertama: kaidah yang menjadi turunan dari kaidah kubraBagian kedua: kaidah yang tidak menjadi turunan dari kaidah kubraTingkatan ketiga: Kaidah-kaidah yang memiliki ruang lingkup sempit dan tidak bersifat umum, karena hanya khusus pada satu bab fikih atau sebagian dari satu bab; dan inilah yang dinamakan dengan dhowabithKedua: dari sisi kesepakatan atau perbedaan pendapat para ulama terhadap isi (maksud) kaidah tersebutTingkatan pertama: Kaidah yang disepakati isi kandungannya di antara seluruh ulama dari lintas mazhabTingkatan kedua: Kaidah yang khusus untuk satu mazhab tertentu, atau yang diamalkan oleh sebagian fuqaha (ulama fikih) tetapi tidak diamalkan oleh mazhab atau fuqaha yang lain, meskipun cakupannya luas dan mencakup banyak permasalahan fikih dari berbagai babDalam kaidah fikih, terdapat banyak sekali kaidah-kaidah yang diberikan oleh para ulama. Sebagaimana yang telah diketahui, tujuan dari hal tersebut adalah untuk memudahkan penuntut ilmu dalam memahami permasalahan-permasalahan ilmu fikih. Berangkat dari hal tersebut, ilmu kaidah fikih itu sendiri terdapat jenis-jenis dan tingkatan-tingkatannya, tidak hanya pada satu jenis atau satu tingkatan saja.Secara garis besar, jenis dan tingkatan kaidah fikih terdapat pada dua hal:Pertama: dari sisi cakupan kaidah dan luasnya jangkauan terhadap cabang-cabang dan permasalahan fikih.Kedua: dari sisi kesepakatan atau perbedaan pendapat para ulama terhadap isi (maksud) kaidah tersebut.Di bawah ini adalah penjelasan dari kedua hal di atas.Pertama: dari sisi cakupan kaidah dan luasnya jangkauan terhadap cabang-cabang dan permasalahan fikihDari poin ini, terbagi menjadi tiga tingkatan:Tingkatan pertama: Kaidah kubra yang cakupan kaidahnya luas dan menyeluruh terhadap cabang dan permasalahan fikihTerdapat lima kaidah kubra yang disepakati oleh para ulama,Pertama:الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا“Segala perkara tergantung pada tujuannya (niatnya).”Kedua:اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّك“Keyakinan tidak hilang karena keraguan.”Ketiga:المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْر“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”Keempat:لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار“Tidak boleh menimbulkan mudharat (bahaya) dan tidak boleh membalas mudharat dengan mudharat.”Kelima:العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ“Kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum.” Inilah lima kaidah kubra yang disepakati oleh para ulama. Sebagian ada yang menambahkannya menjad enam, yaitu kaidah, إِعْمَالُ الكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ“Mengamalkan makna suatu ucapan lebih utama daripada menelantarkannya (membuangnya).” Dari kaidah kubra yang telah disebutkan, nantinya akan terdapat banyak kaidah lainnya sebagai turunan dari kaidah-kaidah tersebut. Itulah di antara sebab mengapa kaidah-kaidah di atas disebut dengan kaidah kubra, karena kaidah-kaidah tersebut merupakan inti di antara kaidah-kaidah yang lainnya.Tingkatan kedua: Kaidah-kaidah yang cakupannya lebih sempit daripada kaidah-kaidah sebelumnya (meskipun tetap bersifat luas dan mencakup banyak hal); di bawah setiap kaidah tersebut terdapat banyak sekali permasalahan fikih yang tidak terhitung jumlahnyaPada kaidah ini terdapat dua bagian:Bagian pertama: kaidah yang menjadi turunan dari kaidah kubraContohnya adalah kaidah:الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المَحْظُوْرَات“Keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang dilarang.” Kaidah ini adalah sebagai turunan atau cabang dari kaidah:المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْر“Kesulitan mendatangkan kemudahan.” Contoh lain, kaidah:لَا يُنْكَرْ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ الاِجْتِهَادِيَّة بِتَغَيُّرِ الأَزْمَانِ“Tidak dapat diingkari bahwa hukum-hukum ijtihadiyah dapat berubah seiring dengan perubahan zaman.” Kaidah ini merupakan turunan atau cabang dari kaidah:العَادَةُ مُحَكَّمة“Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.” Bagian kedua: kaidah yang tidak menjadi turunan dari kaidah kubraContohnya adalah kaidah:الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ، أَوْ بِمِثْلِهِ“Ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lain, atau oleh yang semisalnya.” Dan juga kaidah:التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ“Kebijakan terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan mereka.” Kedua contoh kaidah ini, bukanlah turunan atau cabang dari kaidah kubra.Tingkatan ketiga: Kaidah-kaidah yang memiliki ruang lingkup sempit dan tidak bersifat umum, karena hanya khusus pada satu bab fikih atau sebagian dari satu bab; dan inilah yang dinamakan dengan dhowabithDalam hal ini, seorang ulama bernama Al-Imam Abdul Wahab As-Subki rahimahullah berkata,(الأَمْرُ الكُلِّي الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّات كَثِيْرَة تُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا) وَمِنْهَا مَا لَا يَخْتَصّ بِبَابٍ كَقَوْلِنِا: (اليَقِيْنُ لَا يُرْفَعُ بِالشَّك) وَمِنْهَا مَا يَخْتَصُّ كَقَوْلِنَا: (كُلُّ كَفَّارَةٍ سَبَبُهَا مَعْصِيَة فَهِيَ عَلَى الفَوْر)“Kaidah adalah suatu perkara yang bersifat umum, yang mencakup banyak cabang (masalah) yang dapat dipahami hukumnya melalui kaidah tersebut.”
“Sebagian kaidah tidak khusus pada satu bab, seperti perkataan kita, “Keyakinan tidak hilang karena keraguan.” Dan sebagian khusus pada satu bab, seperti, “Setiap kafarat yang sebabnya adalah kemaksiatan, maka wajib segera dilakukan.” Secara umum, kaidah yang dimaksudkan untuk satu bab tertentu dan mengatur contoh-contoh yang serupa di dalamnya disebut dengan dhabith.Kedua: dari sisi kesepakatan atau perbedaan pendapat para ulama terhadap isi (maksud) kaidah tersebutDari pembahasan ini, terdapat dua tingkatan sebagaimana berikut:Tingkatan pertama: Kaidah yang disepakati isi kandungannya di antara seluruh ulama dari lintas mazhabDi antara contoh dari tingkatan pertama ini adalah kaidah kubra, yang disepakati keabsahannya oleh seluruh ulama, bahkan para ulama dari mazhab yang berbeda-beda.Tingkatan kedua: Kaidah yang khusus untuk satu mazhab tertentu, atau yang diamalkan oleh sebagian fuqaha (ulama fikih) tetapi tidak diamalkan oleh mazhab atau fuqaha yang lain, meskipun cakupannya luas dan mencakup banyak permasalahan fikih dari berbagai babKaidah-kaidah dari tingkatan kedua ini termasuk penyebab adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih dalam menetapkan suatu hukum, berangkat dari perbedaan cara pandang mereka dalam menyusun illat (alasan hukum) terhadap suatu masalah.Contoh dari tingkatan ini adalah kaidah:لَا حُجَّةَ مَعَ الاِحْتِمَالِ النَّاشِئ عَنْ دَلِيْلٍ“Tidak ada kekuatan hujah apabila masih ada kemungkinan makna lain yang didapatkan dari dalil itu sendiri.” Kaidah ini diamalkan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah, tetapi tidak diamalkan oleh ulama Syafi’iyah, sementara Malikiyah mengamalkannya dengan batasan-batasan tertentu.Demikian di antara jenis kaidah fikih dan tingkatan-tingkatannya. Yang terpenting dari pembahasan ini adalah, mengetahui kaidah kubra yang menjadi inti dari kaidah-kaidah fikih lainnya.Semoga bermanfaat. Wallahu Ta’ala a’lam.Baca juga: Faidah Mengenal dan Mempelajari Kaidah Fikih***Depok, 20 Rabi’ul akhir 1447/ 12 Oktober 2025Penulis: Muhammad Zia AbdurrofiArtikel Muslim.or.id Referensi:Al-Mumti’ fil Qowa’id Al-Fiqhiyyah, karya Prof. Dr. Musallam bin Muhammad Ad-Dusary.Al-Wajiz fi Idaahi Qowa’id Al-Fiqhi Al-Kulliyah, karya Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad.
Penulis—semoga Allah merahmatinya—menyebutkan salah satu keindahan dalam pemilihan susunan kata Al-Qur’an: rahasia mengapa nama Al-Wadud (Maha Pengasih) disandingkan dengan Al-Ghafur (Maha Pengampun) dalam firman-Nya, “Dan Dialah Al-Ghafur, Al-Wadud.” (QS. Al-Buruj: 14).
Hal ini karena salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya adalah dengan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka, sangat tepatlah penyandingan dua nama yang mulia ini: Al-Ghafur dan Al-Wadud. Allah Subhanahu wa Ta’ala memiliki cara penyusunan kata yang sangat menakjubkan dalam Al-Qur’an.
Ilmu tentang keindahan susunan kata Al-Qur’an ini—meskipun Allah telah memujinya dalam empat ayat—akan tetapi perhatian terhadap ilmu ini sangat sedikit. Padahal, ilmu ini merupakan salah satu wujud paling agung dari kehebatan Al-Qur’an dan bukti ketinggian kedudukannya, serta sarana untuk memahami hikmah dan maksud-maksudnya. Sebab, terkadang dalam ayat Al-Qur’an ditambahkan satu huruf atau satu kata, atau struktur kalimat diubah, atau dua kata disandingkan demi mencapai makna yang dikehendaki. Barang siapa memahami hal ini, niscaya ia menangkap bagian besar dari maksud al-Qur’an.
Sebagai contoh, dalam firman Allah Ta’ala: “sedangkan kami bertasbih menyucikan nama-Mu” (وَنُقَدِّسُ لَكَ), yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah. Secara kaidah bahasa, kalimat ini bisa saja diungkapkan: “وَنُقَدِّسُكَ” (tanpa huruf lam). Memang secara tata bahasa, huruf lam boleh dihilangkan. Namun, Al-Qur’an memilih bentuk “nuqaddisu laka” (وَنُقَدِّسُ لَكَ) untuk memberi penekanan lebih betapa para malaikat itu menyucikan nama Allah dan mengagungkan-Nya Subhanahu wa Ta’ala. Pemahaman semacam ini termasuk pencapaian tertinggi dalam memahami Al-Qur’an, akan tetapi banyak orang yang lalai dalam memahaminya.
Dahulu, para salaf memahami “penjelasan Al-Qur’an” sebagai pemahaman makna, bukan sekadar hiasan kata. Bahkan, sejumlah ulama terdahulu menulis kitab dengan judul Fahm Al-Qur’an (Pemahaman al-Qur’an). Dan salah satu jalan untuk memahami Al-Qur’an adalah dengan menelaah keindahan susunan katanya. Maka, penuntut ilmu hendaklah memberikan perhatian besar terhadap ilmu ini. Sebab, ilmu ini belum berkembang sempurna, dan keajaibannya tidak akan pernah habis. Namun ilmu ini bergantung pada sejauh mana Allah Subhanahu wa Ta’ala membukakan bagi hamba-Nya pemahaman dalam menangkap rahasia susunan kata Al-Qur’an Al-Karim. Karena cara penyusunan kata dalam Al-Qur’an memiliki berbagai corak dengan tujuan yang beragam.
Semoga Allah memberi kita kesempatan lain untuk menjelaskannya secara lebih luas. Namun, inti pembahasan ini adalah agar engkau mengetahui bahwa salah satu bentuk keindahan susunan kata Al-Qur’an adalah penyandingan nama-nama Allah yang mulia, di antaranya adalah penyandingan dua nama ini, yaitu Al-Wadud dan Al-Ghafur.
=====
وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ لَطَائِفِ التَّصَرُّفِ الْقُرْآنِيّ السِّرَّ فِي اقْتِرَانِ الْوَدُودِ بِالْغَفُوْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ
وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ طَرَائِقِ تَوَدُّدِهِ لِلْخَلْقِ مَغْفِرَتُهُ ذُنُوبَهُمْ فَنَاسَبَ ذَلِكَ الْقَرْنَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ الأَحْسَنَيْنِ الْغَفُورُ وَالْوَدُوْدُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ فِي الْقُرْآنِ تَصَرُّفٌ عَجِيبٌ
وَهَذَا الْعِلْمُ وَهُوَ عِلْمُ التَّصَرُّفِ الْقُرْآنِيّ مَعَ أَنَّ اللَّهَ أَشَادَ بِهِ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْه إِلَا أَنَّ الْعِنَايَةَ بِهِ قَلِيلَةٌ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ مَظَاهِرِ عَظَمَةِ الْقُرْآنِ وَبَيَانِ عُلُوِّهِ وَالْوُقُوفِ عَلَى حِكَمِهِ وَمَقَاصِدِهِ فَقَدْ يُزَادُ حَرْفٌ أَوْ قَدْ يُزَادُ لَفْظٌ أَوْ تُغَيَّرُ جُمْلَةٌ أَو يُقْرَنُ بَيْنَ لَفْظَيْنِ لِمَعْنًى مُقْتَضٍ ذَلِكَ فَمَنْ فَقِهَ هَذَا أَدْرَكَ شَيْئًا عَظِيمًا مِنْ مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ
وَمِنْ ذَلِكَ مَثَلًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَنُقَدِّسُ لَكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ الْكَلَامَ يَسْتَقِيْمُ لُغَةً بِقَوْلِهِ وَنُقَدِّسُكَ فَأَمْكَنَ تَرْكُ اللَّامِ لَكِنْ جَاءَ التَّصَرُّفُ الْقُرْآنِيُّ عَلَى هَذَا النَّحْوِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَأْكِيدِ تَنْزِيْهِ الْمَلَائِكَةِ وَتَعْظِيمِهِمْ لِرَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهَذَا الْمُدْرَكُ مِنْ أَعْظَمِ مَدَارِكِ فَهْمِ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنَّ النَّاسَ مُقَصِّرُوْنَ فِي فَهْمِهِ
وَقَدْ كَانَ عَامَّةُ مَا يُعْرَفُ بِهِ بَيَانُ الْقُرْآنِ فِي السَّلَفِ هُوَ الْفَهْمُ وَصَنَّفَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَوَائِلِ كُتُبًا بِاسْمِ فَهْمِ الْقُرْآنِ وَمِنْ مَقَاصِدِ الْفَهْمِ الِاطِّلَاعُ عَلَى التَّصَرُّفِ الْقُرْآنِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَنِيَ طَالِبُ الْعِلْمِ بِهَذَا فَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَمْ يَقُمْ عَلَى سُوقِهِ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ أَبَدًا بَلْ بِحَسَبِ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْعَبْدِ مِنَ الْفَهْمِ فِي تَصَرُّفِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِي الْقُرآنِ الْكَرِيمِ يَأْتِي عَلَى طَرَائِقَ قِدَدًا وَلِمَقَاصِدَ مُخْتَلِفَةٍ
وَلَعَلَّ اللَّهَ يُهَيِّئُ مَقَامًا آخَرَ نَبْسُطُ الْقَوْلَ فِيهِ لَكِنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مِنْ طَرَائِقِ التَّصَرُّفِ الْقُرْآنِيِّ الِاقْتِرَانُ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَمِنْ جُمْلَتِهَا اقْتِرَانُ هَذَيْن الاِسْمَيْن أَحَدَهِمَا بِالْآخَرِ وَهُوَ الْوَدُودُ وَالْغَفُورُ
بين سفر الدنيا وسفر الآخرة
Oleh:
Ridha Farhawi
رضا فرحاوي
الحمد لله الذي خلق فهدى، وأنعم وأسدى، أحمده تعالى وأشكره على آلائه التي لا نحصي لها عددًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا أحدًا، فردًا صمدًا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبدُالله ورسوله، أكرِمْ به رسولًا وعبدًا، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، الذين أكسبهم شرفًا ومجدًا، والتابعين ومن تبعهم بأمثل طريقة، وأقوم سبيل وأهدى؛ أما بعدُ:
فلا تمشِ يومًا في ثياب مَخْيَلة فإنك من طينٍ خُلقتَ وماءِ
أزور قبور المترفين فلا أرى بهاءً وكانوا قبلُ أهلَ بهاءِ
يعزُّ دفاع الموت عن كل حيلة ويعيا بداء الموت كل دواءِ
أمامك يا نومانُ دارُ سعادةٍ يدوم البقا فيها ودار شقاءِ
خُلقتَ لإحدى الغايتين فلا تَنَمْ وكُنْ بين خوف منهما ورجاءِ
Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah menciptakan, lalu memberi petunjuk dan melimpahkan kenikmatan. Saya haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung jumlahnya.
Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala semata yang tidak memiliki sekutu, Tuhan Yang Maha Esa Yang menjadi tempat bergantung. Saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam adalah hamba dan rasul Allah, sungguh rasul dan hamba yang paling mulia, semoga salawat, salam, dan keberkahan selalu tercurah kepada beliau, dan kepada keluarga dan para sahabat – yang beliau tularkan kemuliaan kepada mereka – serta para Tabi’in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya dan menapaki jalan yang berpetunjuk. Amma ba’du:
فَلَا تَمْشِ يَوْمًا فِي ثِيَابِ مَخِيلَة فَإِنَّكَ مِنْ طِينٍ خُلِقَْتَ وَمَاءِ
Jangan pernah berjalan dengan penuh kesombongan
Karena kamu tercipta dari tanah dan air
أَزُورُ قُبُورَ الْمُتْرَفِينَ فَلَا أَرَى بَهَاءً وَكَانُوا قَبْلُ أَهْلَ بَهَاء
Saya mengunjungi kuburan orang-orang yang hidup mewah, tapi tidak melihat.
Kemewahan, padahal dulu mereka berlimpah kemewahan
يَعِزّ دِفَاعَ الْمَوْتِ عَنْ كُلِّ حِيلَة وَيَعْيا بِدَاءِ الْمَوْتِ كُلُّ دَوَاء
Tidak mampu menolak kematian dengan segala cara
Dan segala obat tidak dapat mengobati penyakit maut
أَمَامَكَ يَا نَوْمَانُ دَارُ سَعَادَة يَدُومُ الْبَقَا فِيهَا وَدَارُ شَقَاء
Di depanmu, wahai tukang tidur! Ada negeri kebahagiaan.
Yang kekal abadi, juga negeri kesengsaraan.
خُلِقَْتَ لِإِحْدَى الْغَايَتَيْنِ فَلَا تَنَمْ وَكُنْ بَيْنَ خَوْفِ مِنْهُمَا وَرَجَاء
Kamu tercipta untuk salah satu tujuan itu, maka janganlah tidur!
Dan tetaplah di antara takut dan harap terhadap keduanya!
أيها الأحبة في الله:
لي معكم اليوم ثلاث وقفات:
أما الوقفة الأولى فهي:
وقفة مع السفر:
السفر سفران؛ فأعظم سفر هو سفر إلى الله والدار الآخرة، وإن من الأمور التي يوافقك عليها جميع المؤمنين، ولا يخالفك فيها أحد من المسلمين، أن هذه الدنيا إنما هي جسرٌ يعبره العابرون، ويجتازه المارُّون، قد قدموا من دار لينتقلوا إلى دار، قد قدموا من عالم العدم؛ لينتقلوا إلى دار الخلود: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان: 1]، ويقول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ [الأنعام: 62]، ثم هم إما إلى نعيم مقيم، أو جحيم أليم؛ قال العلي الخبير: ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى: 7]، فنحن في هذه الدنيا في سفر دائم، لا أحد منا يعلم متى يُقال له: حطَّ رحالك، وودِّع أهلك ومالك، واعرض علينا أعمالك؛ عندئذٍ ينتهي السفر؛ قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: 34].
ولئن كان السفر الذي نسافره في هذه الدنيا قطعةً من العذاب، فكيف بالسفر لملاقاة العزيز الوهاب؟! فالسفر شاقٌّ وطويل، والزاد ضئيل وقليل، ونهاية السفر، إما إلى نار وجحيم، وإما إلى جنات النعيم:
فحيَّ على جنات عدن فإنها منازلُك الأولى وفيها المخيَّمُ
ولكننا سبيُ العدوِّ فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلَمُ
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ
Wahai saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala!
Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tiga pembahasan kepada kalian:
Pembahasan pertama: jenis perjalanan
Perjalanan kita terdiri atas dua perjalanan, dan yang paling agung adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan negeri akhirat.
Suatu hal yang seluruh kaum Mukminin pasti bersepakat denganmu tanpa ada yang menyelisihinya adalah bahwa dunia ini merupakan jembatan yang diseberangi dan dilalui oleh manusia, mereka datang dari suatu kehidupan dan berpindah ke kehidupan lainnya, karena datang dari negeri yang fana menuju negeri yang kekal.
“Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?” (QS. Al-Insan: 1).
Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman: “Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala” (QS. Al-An’am: 62).
Setelah itu, antara mereka menuju kenikmatan yang kekal atau azab yang pedih. Allah Subhanahu Wa Ta’ala Yang Maha Tinggi dan Maha Mengetahui berfirman: “Satu golongan di surga dan satu golongan di neraka yang menyala-nyala.” (QS. Asy-Syura: 7).
Kita di dunia ini sedang dalam perjalanan yang tiada henti. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui kapan akan dikatakan kepadanya, “Turunkan barang-barangmu, sampaikan perpisahan dengan keluarga dan hartamu, dan serahkan kepada kami amalan-amalanmu.” Ketika itulah perjalanan di dunia usai, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat (pula) meminta percepatan.” (QS. Al-A’raf: 34).
Sungguh perjalanan yang kita lakukan di dunia ini sudah menjadi potongan dari siksaan, lalu bagaimana lagi dengan perjalanan untuk berjumpa dengan Yang Maha Perkasa dan Maha Pemberi karunia? Perjalanan ini amatlah berat dan panjang, sedangkan perbekalan masih sedikit dan terbatas. Lalu ujung dari perjalanan ini antara menuju neraka dan siksaan, atau menuju surga yang penuh dengan kenikmatan.
فَحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإِنَّهَا مَنَازِلُكَ الْأُولَى وَفِيْهَا الْمُخَيَّمُ
Marilah menuju surga Adn, karena ia adalah
Tempat asalmu, dan di dalamnya terdapat kemah
وَلَكِنَّنَا سَبِيُ الْعَدُوِّ فَهْلْ تَرَى نَعُودُ إِلَى أَوْطَانِنَا فَنَسْلَمُ
Namun kita tersandera oleh musuh, apakah menurutmu
Kita dapat kembali ke tanah air kita dengan selamat?
فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيْبَةٌ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيْبَةُ أَعْظَمُ
Apabila kamu tidak mengetahuinya, maka itu musibah
Dan apabila kamu mengetahui, maka itu musibah lebih besar lagi
والنوع الثاني من السفر: سفر راحةٍ واستجمام، فسافر لترى البُلدان والأمصار، سافر لترى العجائب والآثار:
تلك الطبيعةُ قِفْ بنا يا سارِ حتى أريَك بديع صنع الباري
فالأرض حولك والسماء اهتزَّتا لروائع الآيات والآثارِ
الماء الذي لا يجري يتغير ويحمل الأنجاس، والشمس لو بقيت واقفة في السماء لملَّها الناس، والأُسْدُ لولا فراقُ الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يُصِب.
فمن آداب السفر ألَّا تسافر إلى بلدان مشبوهة، وأماكن بالفساد معروفة، فهذا ليس سفرَ طاعةٍ، بل هو سفر معصية، وكل لحظة تقضيها في تلك البلدان، فأنت في سخط وغضب من الواحد الديان، ألَا تخشى أن تُقبَضَ روحك هناك، وأن تموت في سخط ومعصية مولاك:
مشيناها خطًى كُتِبت علينا ومن كُتبت عليه خطًى مشاها
ومن كانت منيَّتُه بأرضٍ فليس يموت في أرضٍ سواها
Sedangkan jenis kedua yaitu perjalanan untuk rekreasi. Lakukanlah perjalanan, agar dapat melihat berbagai negeri! Lakukanlah perjalanan, agar dapat melihat berbagai keajaiban dan peninggalan.
تِلْكَ الطَّبِيْعَةُ قِفْ بِنَا يَا سَارِِ حَتَّى أُرِيَكَ بَدِيْعَ صُنْعِ الْبَارِي
Inilah alam, berhentilah sejenak bersama kami, wahai musafir!
Agar Kutunjukkan kepadamu keajaiban ciptaan Sang Pencipta
فَالْأَرْضُ حَوْلَكَ وَالسَّمَاءُ اهْتَزَّتَا لِرَوَائِعِ الْآيَاتِ وَالآثَارِِ
Bumi di sekelilingmu dan langit bergetar
Karena luar biasanya tanda-tanda kekuasaan dan penciptaan-Nya
Air yang tidak mengalir akan berbau dan menampung banyak najis, seandainya matahari diam di tempat pasti manusia bosan padanya, seandainya singa-singa tidak meninggalkan liangnya pasti tidak bisa mendapatkan mangsa, dan seandainya anak panah tidak meninggalkan busurnya pasti tidak akan menepati sasarannya.
Di antara adab bepergian adalah tidak pergi ke negeri yang banyak syubhat di dalamnya, dan tempat-tempat yang dikenal dengan kerusakannya. Ini bukanlah perjalanan untuk ketaatan, tapi justru perjalanan untuk kemaksiatan. Setiap saat yang kamu lalui di negeri-negeri seperti itu, kamu berada dalam kemarahan dan kemurkaan Sang Kuasa. Tidakkah kamu takut nyawamu dicabut di sana, dan meninggal dunia dalam kemurkaan dan kemaksiatan terhadap Tuhanmu?
مَشَيْنَاهَا خُطًى كُتِبَتْ عَلَيْنَا وَمَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ خُطًى مَشَاهَا
Dicatat atas kami, langkah-langkah yang kita ayunkan
Juga dicatat bagi pelakunya, setiap langkah yang dia ayunkan
وَمَنْ كَانَتْ مَنِيَّتُهُ بِأَرْضٍ فَلَيْسَ يَمُوتُ فِي أَرْضٍ سِوَاهَا
Siapa yang kematiannya telah ditetapkan di suatu negeri
Maka tidak akan mati di negeri lainnya
الوقفة الثانية: مع سفر المعصية:
السفر إلى شواطئ العُرْيِ والفجور، وإلى أماكن التبرج والسُّفور، منكرات مخزية ومبكية، نراها في شواطئنا البحرية، فما يحدث على شواطئنا منكَرٌ، لا يرضاه عاقل ولا رب البشر، الله تبارك وتعالى سخر لنا البحر وجعله نعمة، بل هو آية من آياته ومنة؛ مناظر لغروب الشمس جميلة، ولوحة يرسمها المبدع كل ليلة، مياه ورمال، حسن وجمال؛ قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الجاثية: 12]، ولكن مع كل أسف، جاء الإنسان فأفسد، وعصى الواحد الأحد؛ اختلاط وفجور، عُرْي وسفور:
فيا عجبًا كيف يُعصَى الإله أم كيف يجحده الجاحدُ
وله في كل شيء آية تدل على أنه واحدُ
Pembahasan kedua: perjalanan untuk kemaksiatan
Perjalanan menuju pantai dan tempat-tempat terpampangnya aurat dan menyimpang dari kehormatan diri merupakan kemungkaran yang hina dan menyedihkan. Pemandangan ini dapat kita saksikan di pantai-pantai laut kita. Apa yang ada di pantai-pantai itu merupakan kemungkaran, tidak akan diterima oleh akal sehat, terlebih lagi oleh Tuhan segenap manusia.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan laut bagi kita dan menjadikannya sebagai kenikmatan. Ia merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan karunia-Nya. Pemandangan matahari tenggelam yang begitu indah, kanvas yang dilukis oleh Sang Pencipta setiap malam menjelang. Juga air dan pasirnya, sungguh keindahan yang mempesona. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
“Allahlah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Jatsiyah: 12).
Namun, sangat disayangkan, manusia hadir dan berbuat kerusakan di sana, melakukan kemaksiatan terhadap Sang Kuasa, bercampur-baur laki-laki dan perempuan, perbuatan keji, pengumbaran aurat, dan tindakan-tindakan asusila lainnya.
فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ اْلجَاحِدُ
Sungguh mengherankan, bagaimana Tuhan dimaksiati
Dan bagaimana ada orang yang mengingkari-Nya?
وَلَهُ فِي كُلِّ شَيءٍ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ
Padahal, dalam segala hal terdapat tanda kekuasaan-Nya
Yang menunjukkan bahwa Dialah Yang Maha Esa
أسر تزعُم أنها مسلمة متمسكة بدينها، تتفنن نساؤها وبناتها في إبراز مفاتنها، أين المروءة؟ أين الرجولة؟ ما هذه المنكرات؟ أين الشهامة؟ أين الغَيرة على الحُرُمات؟ رجل يسبح شبه عارٍ أمام بناته، أمٌّ تسبح شبه عارية أمام أبنائها، وبنت تفنَّنت في إبراز مفاتنها؛ جاء في مسند الإمام أحمد عن أم الدرداء رضي الله عنها، قالت: ((خرجتُ من الحمَّام، فلقِيَني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ فقالت: من الحمام، فقال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تنزِع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا وهي هاتكةٌ كلَّ سترٍ بينها وبين الرحمن عز وجل)).
هذا حمام فقط، قال فيه ما قال، فكيف بالتي تنزع ثيابها في الشواطئ أمام الرجال؟ عيون للشباب تترصدها، وقلوب مريضة تنهَش جسدها، سقط الحياء، وهُتِكَ السِّتار، وغضِبَ الجبَّار.
Ada banyak keluarga yang mengaku sebagai keluarga Muslim dan teguh berpegang pada agamanya, tapi istri dan putri-putrinya menebar fitnah dengan menampakkan auratnya. Di mana harga diri? Di mana kejantanan suami? Mengapa terjadi berbagai kemungkaran ini? Di mana kehormatan diri? Di mana kecemburuan terhadap hal-hal yang terhormat? Ada ayah yang berenang setengah telanjang di depan putri-putrinya, ibu berenang setengah telanjang di hadapan putra-putranya, dan putri yang menebar fitnah dengan mengumbar auratnya!
Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Ummu ad-Darda Radhiyallahu ‘anha, ia menceritakan, “Aku pernah pulang dari pemandian umum. Lalu aku berpapasan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam dan beliau pun bertanya, ‘Dari mana, wahai Ummu Ad-Darda?’ Aku menjawab, ‘Dari pemandian umum.’ Beliau lalu bersabda, ‘Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Tidaklah ada seorang wanita yang melepas pakaiannya selain di rumah salah satu ibunya, melainkan ia telah merenggut seluruh penutup antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.’” (HR. Ahmad).
Di pemandian umum saja, Nabi mengucapkan hal yang demikian, lalu bagaimana dengan wanita yang melepas pakaiannya di pantai-pantai di hadapan para pria? Mata para pemuda mengamatinya dan hati-hati yang berpenyakit melahap jasadnya, telah runtuh rasa malu, telah terenggut tabir, dan telah murka Sang Kuasa.
الوقفة الثالثة: رسالة شكر وعتاب للشابات والشباب:
أما شكري، فأوجِّهه لمن عرَف ربَّه، وسلك طريقه ودربه:
أُهْدِي الشباب تحية الإكبار هم كَنْزُنا الغالي وسرُّ فَخاري
هل كان أصحاب النبي محمدٍ إلا شبابًا شامخَ الأفكارِ
أيها الشاب، انتبِهْ؛ فالشباب فترة تمر ولا تعود، ومرحلة للنجاح والصعود، الشباب ساعة، فاغتنمها في الطاعة، الشباب قوة، فلا تفسدها في الشهوة، الشباب مرحلة ستُسأل عنها فيما قضيتها، وفيما أفنيتها، الشاب المسلم لا يعرف الفراغ؛ فهو يستغل وقته قدر المستطاع، الشباب عافية وصحة كأنها تاج من ذهب، والكل حتمًا سيزول ويذهب، أيها الشاب، اغتنم شبابك قبل الهَرَمِ، فسيأتي يومًا على شبابك ستندم، لو سألتَ شيخًا: ماذا تتمنى؟ لتمنَّى أن يعيش يومًا من شبابه، يومًا من عافيته وصحته وقوته، يومًا بلا أمراض ولا آلام، يومًا بلا تعب ولا أسقام، يومًا يستطيع فيه أن يقف على قدميه، أن يمشي أن يجري، فهذا أقصى أمانيه.
Pembahasan ketiga: ucapan rasa syukur sekaligus kritik bagi para pemuda-pemudi
Adapun rasa syukurku saya tujukan kepada pemuda dan pemudi yang mengenal Tuhannya dan menempuh jalan-Nya:
أُهْدِي الشَّبَابَ تَحِيَّةَ الْإِكْبَارِ هُمْ كَنْزُنَا الْغَالِي وَسِرُّ فَخَارَي
Saya hadiahkan bagi para pemuda salam hormatku
Merekalah harta simpanan kita yang berharga dan rahasia rasa banggaku
هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِي مُحَمّدٍ إِلَّا شَبَابًا شَامِخَ الْأَفْكَارِِ
Bukankah para sahabat Nabi Muhammad dahulu
Tidak lain adalah para pemuda yang berpikiran luhur
Wahai para pemuda, waspadalah! karena masa muda adalah masa yang akan berlalu dan tidak akan kembali. Fase untuk meraih kesuksesan dan kebangkitan. Masa muda hanya sekejap, maka manfaatkanlah untuk berbuat taat. Masa muda adalah masa kuat, maka jangan merusaknya dalam syahwat. Masa muda adalah fase hidup yang akan dimintai pertanggungjawabannya, untuk apa digunakan dan dalam hal apa dihabiskan.
Pemuda Muslim tidak mengenal waktu kosong, karena ia akan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Masa muda adalah masa sehat, seakan-akan ia adalah mahkota emas. Namun, semua itu akan hilang dan lenyap. Wahai para pemuda, manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tua, karena akan datang hari ketika kamu menyesali masa mudamu.
Seandainya kamu bertanya orang yang sudah sepuh, “Apa yang Anda harapkan?” Pasti dia berharap dapat hidup sehari lagi di masa mudanya, hidup sehari dengan kesehatan dan kekuatannya, sehari tanpa penyakit dan rasa sakit, sehari tanpa rasa letih dan perih, sehari yang dia mampu berdiri dengan dua kakinya, berjalan dan berlari. Inilah puncak angan-angannya.
أما عتابي فإليك أيها الشاب، يا من فتَّشنا عنك في المسجد فما وجدناك، وبحثنا عنك بين الصفوف فما رأيناك، زُرْتَنا في رمضان والآن هجرتنا، سُرِرْنا بإقبالك في تلك الأيام والآن أحزنتنا، مكان سجودك اشتاق إليك، والمؤذِّن خمس مرات في اليوم يناديك، أقْبِلْ على ربِّك، أقبِل على الفلاح، أقبل على سعادتك، فهنا السر، وهنا المفتاح؛ مفتاح سعادتك في خطوات تمشيها، ودقائق في بيت الله تقضيها.
أيها الشاب، إياك وأصدقاءَ السوء، أصحابك جنتك، وأصحابك نارك، فاختر بين أصحاب وأصحاب، فالنار دركات، والجنة درجات وأبواب، صاحبك قد يكون طريقك إلى الجنة؛ فبه تسعَد والله عنك يرضى، وقد يكون طريقك إلى النار فبه تخسر وتشقى.
أنت في نعمة أيها الشاب؛ ﴿ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [البقرة: 211].
Adapun kritikku kepadamu, wahai pemuda! Wahai orang yang kami cari di masjid tapi kami tidak menemukannya! Kami cari di antara shaf-shaf salat tapi kami tidak melihatnya! Kamu mengunjungi kami pada bulan Ramadhan, tapi sekarang kami campakkan kami lagi. Kami bahagia dengan kehadiranmu pada masa-masa itu, tapi sekarang kami bersedih kembali. Tempat sujudmu sudah rindu padamu. Muazin yang mengumandangkan azan lima kali sehari itu memanggilmu.
Kembalilah kepada Tuhanmu! Sambutlah kesuksesanmu! Datanglah menuju kebahagiaanmu! Di sinilah rahasianya, dan di sinilah kuncinya, kunci kebahagiaanmu ada di setiap langkah yang kamu ayunkan menuju masjid dan setiap menit yang kamu habiskan di Rumah Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Wahai pemuda, jauhilah teman-teman yang buruk, karena temanmu adalah surgamu, atau sebaliknya, temanmu adalah nerakamu, maka pilihlah teman yang baik di antara teman-teman itu. Neraka itu punya tingkat-tingkat kedalaman, dan surga juga punya tingkat-tingkat derajat dan punya pintu-pintu. Temanmu bisa jadi adalah jalanmu menuju surga, sehingga dengannyalah kamu dapat bahagia dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dapat ridha kepadamu. Temanmu juga bisa menjadi jalanmu menuju neraka, sehingga dengannyalah kamu merugi dan sengsara.
Kamu sekarang berada dalam kenikmatan, wahai pemuda! “Dan siapa yang menukar nikmat Allah (dengan kekufuran) setelah (nikmat itu) datang kepadanya, sesungguhnya Allah Maha Keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 211).
يا رب، أكرمتنا فلك الحمد، ورزقتنا فلك الحمد، وعافَيْتَنا فلك الحمد، وسترتنا فلك الحمد، فلك الحمد دائمًا وأبدًا.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطك، اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ya Tuhanku, Engkau telah memuliakan kami, maka segala puji bagi-Mu, telah memberi rezeki kepada kami, maka segala puji bagi-Mu, telah menutup aib kami, maka segala puji bagi bagi-Mu, segala puji hanya bagi-Mu selama-lamanya.
Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari lenyapnya kenikmatan-Mu, berubahnya keselamatan-Mu, mendadaknya azab-Mu, dan segala kemurkaan-Mu!
Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami, rahmatilah orang-orang yang telah wafat di antara kami, sampaikanlah kami pada harapan-harapan kami yang Engkau ridhai, dan tutuplah usia kami dengan amal saleh. Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami, dan apabila Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.
Sumber:
https://www.alukah.net/sharia/1001/164615/بين-سفر-الدنيا-وسفر-الآخرة/
Sumber artikel PDF
🔍 Cara Menghadiahkan Al Fatihah, Istri Yang Sabar, Pertanyaan Tauhid, Haid Sebulan 2x
Visited 208 times, 1 visit(s) today
Post Views: 226
<img class="aligncenter wp-image-43307" src="https://i0.wp.com/konsultasisyariah.com/wp-content/uploads/2023/10/qris-donasi-yufid-resized.jpeg" alt="QRIS donasi Yufid" width="741" height="1024" />
Daftar Isi
ToggleGambaran surgaPenghuni surga akan memiliki paras yang tampan atau cantik jelita dan tidak pernah menuaSeluruhnya adalah keabadianSegala hal yang diinginkan hati tersedia, penghuninya bebas memilih sesuai selera dan kehendaknyaBidadari dan istri-istri yang suciMelihat wajah AllahGambaran nerakaPenghuninya akan menjadi bahan bakar api nerakaMakanan dan minuman penduduk neraka sangatlah menjijikkanAzab yang pedih dan bertingkat-tingkatPenutupSetiap insan yang beriman tentu meyakini bahwa kehidupan dunia ini bukanlah tujuan akhir. Dunia hanyalah tempat singgah sementara, tempat manusia diuji dengan ketaatan dan kesabaran sebelum menuju tempat kembali yang abadi: surga atau neraka. Dua tempat ini bukan sekadar kisah simbolik, melainkan realita yang pasti terjadi, sebagaimana diberitakan dalam Al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.Dengan memahami gambaran surga dan neraka sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan sunnah, seorang mukmin akan terdorong untuk berlomba dalam ketaatan dan menjauh dari maksiat. Ia tidak lagi tertipu oleh gemerlap dunia, karena ia menyadari bahwa di balik kehidupan fana ini, ada balasan kekal yang menanti setiap amal perbuatan dan gerak geriknya.Gambaran surgaTentu saja gambaran surga tidak akan terlepas dari segala kenikmatannya yang tiada tara sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam hadis qudsi,أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ“Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku siapkan bagi para hamba-Ku yang saleh (kenikmatan) yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah terdengar sebelumnya oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia.” (HR. Bukhari no. 4779 dan Muslim no. 2824)Berikut ini adalah beberapa gambaran singkat mengenai surga dan beragam kenikmatan di dalamnya yang telah dijelaskan oleh Allah Ta’ala dan Nabi-Nya Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam: Penghuni surga akan memiliki paras yang tampan atau cantik jelita dan tidak pernah menuaNabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتْفِلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ عُودُ الطِّيبِ وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ “Sesungguhnya kelompok pertama yang akan masuk surga adalah orang-orang yang wajahnya bagaikan rembulan di malam purnama. Kemudian yang setelahnya, bagaikan bintang di atas langit yang sangat terang cahayanya, mereka tidak pernah buang hajat dan air kecil, tidak buang ingus dan ludah. Sisir yang mereka pakai terbuat dari emas, keringat yang keluar dari tubuhnya seperti misk, sanggulnya berupa kayu gaharu, istri-istri mereka adalah bidadari, mereka diciptakan di atas satu orang, dengan paras bapak mereka Adam, sepanjang enam puluh dira’ menjulang ke langit.“ (HR Bukhari no. 3245 dan Muslim no. 2834)Ketampanan atau kecantikan penghuni surga selalu diperbarui setiap hari dengan angin sepoi-sepoi yang berembus ke arah mereka. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,إنَّ في الجَنَّةِ لَسُوقًا، يَأْتُونَها كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمالِ فَتَحْثُو في وُجُوهِهِمْ وثِيابِهِمْ، فَيَزْدادُونَ حُسْنًا وجَمالًا، فَيَرْجِعُونَ إلى أهْلِيهِمْ وقَدِ ازْدادُوا حُسْنًا وجَمالًا، فيَقولُ لهمْ أهْلُوهُمْ: واللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْنًا وجَمالًا، فيَقولونَ: وأَنْتُمْ، واللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْنًا وجَمالًا“Sesungguhnya di surga terdapat pasar yang mereka datangi setiap Jumat. Angin utara berembus ke wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah cantik dan tampan. Ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka telah bertambah cantik dan tampan. Keluarga mereka berkata, ‘Demi Allah, kalian telah bertambah cantik dan tampan sepeninggal kami.’ Mereka menjawab, ‘Demi Allah, kalian juga telah bertambah cantik dan tampan.'” (HR. Muslim no. 2833) Seluruhnya adalah keabadianPara penghuni surga akan kekal di dalamnya selama-lamanya dengan segala kenikmatannya yang abadi. Allah Ta’ala berfirman,أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ“Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. At-Taubah: 89) Segala hal yang diinginkan hati tersedia, penghuninya bebas memilih sesuai selera dan kehendaknyaAllah Ta’ala berfirman,وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya.” (QS. Az-Zukhruf: 71)Di antaranya ada beragam jenis buah-buahan dan daging burung. Sebagaimana firman Allah Ta’ala,وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ , وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ“Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.” (QS. Al-Waqi’ah: 20-21)Terdapat juga segala jenis minuman, di antaranya adalah sungai dan lautan dengan empat rasa: air susu, madu, khamr, dan air segar. Allah Ta’ala berfirman dalam Al-Qur’an, مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ “Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah (seperti taman); mengalir sungai-sungai di dalamnya; sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari arak yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring.” (QS. Muhammad: 15)Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda,إنَّ في الجنَّةِ بحرَ الماءِ ، وبحرَ الخمرِ ، وبحرَ العسَلِ ، وبحرَ اللَّبنِ ، ثمَّ تشقَّقُ بعدُ منهُ الأنهارُ“Sesungguhnya di surga ada lautan air, lautan khamr, lautan madu, dan lautan susu. Kemudian sungai-sungai akan mengalir darinya.” (HR. Tirmidzi no. 2571 dan Ahmad no. 20052) Bidadari dan istri-istri yang suciAllah Ta’ala telah berbicara mengenai hal ini dalam firman-Nya, وَحُورٌ عِين # كَأَمۡثَٰلِ ٱللُّؤۡلُوِٕ ٱلۡمَكۡنُونِ“Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan apik.” (QS. Al-Waqi’ah: 22-23)Allah Ta’ala menjelaskan sifat bidadari yang lainnya, إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءا # فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا # عُرُبًا أَتۡرَابا“Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) tanpa proses melahirkan. Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Penuh cinta lagi sebaya umurnya.” (QS. Al-Waaqi’ah: 35-37)Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah bercerita,وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا“Kalau seandainya wanita penduduk surga melongokkan kepalanya ke dunia, tentu cahayanya akan menerangi langit dan bumi, serta menyebarkan aroma wangi ke seluruh sudutnya. Dan sungguh penutup kepala yang dipakai (bidadari) itu lebih baik dari dunia dan seisinya.“ (HR. Bukhari no. 2796) Melihat wajah AllahMelihat wajah Sang Pencipta merupakan puncak dari segala bentuk kenikmatan, hal ini Allah khususkan bagi para penghuni surga, sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Shuhaib Ar-Rumi radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ – قَالَ – يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ – قَالَ – فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ثم تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } “Apabila penduduk surga telah masuk ke dalamnya, maka Allah Tabaraka wa Ta’ala berkata, ‘Apakah kalian menginginkan sesuatu yang Aku tambah lagi bagi kalian?’ Mereka menjawab, ‘Bukankah Engkau telah menjadikan wajah kami putih berkilau? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga serta menyelamatkan kami dari neraka?’ Nabi meneruskan, ‘Pada saat itu, Allah membuka tabir yang menutupi-Nya. Dan tidak ada yang diberikan kepada mereka sesuatu yang paling mereka cintai melainkan diberinya kenikmatan bisa melihat Rabbnya.’ Kemudian beliau membaca firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahan (kenikmatan melihat Allah).” (QS. Yunus: 26). (HR. Muslim no. 181)Allah Ta’ala juga berfirman,وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ # إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ“Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabbnyalah mereka melihat.” (QS. Al-Qiyamah: 22-23)Baca juga: Empat Kunci Masuk SurgaGambaran nerakaSebaliknya, gambaran neraka tidak jauh dari segala azabnya yang sangat-sangat mengerikan. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ غَطَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ“Surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis.” (HR Muslim no. 2359)Berikut adalah beberapa gambaran kengerian neraka: Penghuninya akan menjadi bahan bakar api nerakaAllah Ta’ala berfirman,يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)Disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan perbandingan untuk menjelaskan betapa panasnya api neraka. Beliau bersabda, نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِى يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ “Api yang dipergunakan untuk memasak oleh anak cucu Adam, panasnya hanyalah bagian dari tujuh puluh cabang dari panasnya neraka Jahanam.“ (HR. Bukhari no. 3265 dan Muslim no. 2843) Makanan dan minuman penduduk neraka sangatlah menjijikkanDisebutkan beberapa makanan mereka, di antaranya adalah pohon dhari’, sebagaimana firman Allah Ta’ala, لَّيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيع“Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri.” (QS. Al-Ghasyiyah: 6)Dhari’ adalah sejenis pohon yang memiliki duri besar, yang rasanya sangat pahit dan sangat panas lagi berbau busuk.Allah Ta’ala juga berfirman,إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ * طَعَامُ الْاَثِيْمِ * كَالْمُهْلِ ۛ يَغْلِيْ فِى الْبُطُوْنِۙ * كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ“Sesungguhnya pohon zaqqum itu (adalah) makanan orang yang banyak berdosa. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang amat panas.“ (QS. Ad-Dukhan: 43-46)Dan masih banyak lagi dalil dalil yang menjelaskan makanan menjijikkan lainnya bagi penghuni neraka.Allah Ta’ala berfirman menggambarkan minuman penduduk neraka,وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ “…dan mereka diberi minum air yang mendidih sehingga memotong usus mereka.” (QS. Muhammad: 15)Nanah dan darah juga menjadi minuman mereka. Allah Ta’ala berfirman,وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنۡ غِسۡلِين “Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.” (QS. Al-Haqqah: 36)Adapula cairan tembaga yang mendidih yang menjadi minuman mereka. Allah Ta’ala berfirman,وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً “Dan jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi pertolongan dengan air seperti cairan tembaga yang mendidih yang membakar wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” (QS. Al-Kahfi: 29) Azab yang pedih dan bertingkat-tingkatSebagaimana di surga, balasan di neraka akan sesuai dengan amalnya. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda tentang penghuni neraka, مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ “Di antara para penghuni neraka, ada yang disiksa dengan tenggelam dalam api sampai mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada lagi yang sampai ke pusar, dan ada yang tenggelam sampai ke lehernya.“ (HR. Muslim no. 2845)Sedangkan azab neraka yang paling ringan adalah dengan diletakkan bara api pada telapak kaki penghuninya hingga mendidihlah otaknya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,إنَّ أهْوَنَ أهْلِ النَّارِ عَذابًا يَومَ القِيامَةِ، لَرَجُلٌ تُوضَعُ في أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ، يَغْلِي مِنْها دِماغُهُ“Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya di neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan bara api di telapak kakinya sehingga otaknya mendidih.” (HR. Bukhari no. 6561 dan Muslim no. 213)Waliyadzubillah.PenutupSetelah kita merenungi dahsyatnya azab neraka dan indahnya kenikmatan surga, sudah sepantasnya hati ini tergerak untuk bertobat, memperbanyak amal saleh, dan memperkuat iman. Surga bukanlah tempat bagi orang yang hanya berharap tanpa usaha, dan neraka bukanlah takdir yang tak dapat dihindari bagi mereka yang bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Allah Ta’ala mengingatkan dalam firman-Nya,وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” (QS. Āli ‘Imrān: 133)Jadikan surga sebagai cita-cita tertinggi dan jadikan takut kepada neraka sebagai pengingat agar langkah kita tidak menyimpang. Semoga Allah Ta’ala meneguhkan hati kita di atas ketaatan, melindungi kita dari godaan dunia yang menipu, dan mengumpulkan kita kelak di dalam surga-Nya. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.Baca juga: Empat Permohonan Penduduk Neraka***Penulis: Muhammad Idris, Lc.Artikel Muslim.or.id
Silaturahim termasuk amal besar yang sangat ditekankan dalam Islam. Namun, banyak di antara kita yang belum memahami siapa saja kerabat yang termasuk dalam lingkaran silaturahim yang wajib disambung. Islam mengajarkan bahwa kewajiban ini tidak terbatas pada kerabat dekat atau ahli waris saja, tetapi mencakup setiap keluarga dari pihak ayah maupun ibu. Tulisan ini menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam lingkaran tersebut, serta tingkatan terbaik dalam menjaga hubungan silaturahim.Kerabat yang wajib disambung (silaturahim) ternyata lebih luas dari sekadar lingkaran ahli waris, lebih luas dari lingkaran mahram, bahkan lebih luas dari lingkaran ‘ashabah (garis keturunan laki-laki). Mereka mencakup seluruh kerabat seorang muslim, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Daftar Isi tutup 1. 1. Menyambung dan berbuat baik kepada kerabat yang memusuhi dan menyakiti. 2. 2. Menyambung dan berbuat baik kepada kerabat yang memutus hubungan. 3. 3. Menyambung kerabat yang memang sudah menjaga hubungan. 4. 4. Menahan diri dari menyakiti semua kerabat. Adapun tingkatan tertinggi dalam menyambung silaturahim adalah sebagai berikut:1. Menyambung dan berbuat baik kepada kerabat yang memusuhi dan menyakiti.Inilah tingkat yang paling mulia, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:«أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ»“Sedekah yang paling utama adalah kepada kerabat yang memendam kebencian.” (HR. Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani). 2. Menyambung dan berbuat baik kepada kerabat yang memutus hubungan.Bisa jadi mereka tidak berbuat jahat, hanya saja tidak mau memulai silaturahim. Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda:«لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا»“Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu yang sekadar membalas (kebaikan). Namun yang benar-benar menyambung adalah orang yang tetap menyambung meski diputuskan.” (HR. Bukhari). 3. Menyambung kerabat yang memang sudah menjaga hubungan.Dalam hal ini, engkau membalas kebaikan dengan kebaikan, meski keutamaan tetap berada pada pihak yang lebih dahulu memulai. 4. Menahan diri dari menyakiti semua kerabat.Inilah tingkatan yang paling rendah, namun tetap bagian dari silaturahim. Bahasan dari Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid:الأقارب الذين تجب صلتهم دائرتهم أوسع من دائرة الورثة، وأوسع من دائرة المحارم، وأوسع من دائرة العصبة، فهم أقارب المسلم من جهة أبيه وأمه، وأعلى درجات الصلة: ١. الصلة والإحسان للقريب المعادي والمسيء، كما جاء في حديث «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» [رواه أحمد، وصححه الألباني]. ٢. الصلة والإحسان للقريب القاطع، فقد لا يكون مسيئًا ولكن لا يبادر بالصلة، وفي حديث: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» [رواه البخاري]. ٣. الصلة للقريب المواصل، ومقابلة الإحسان بالإحسان، فيكون فضل المبادرة له ثم المكافأة منك. ٤. كف الأذى عن جميع الأقارب، وهي أدنى المراتب. Baca juga: Berbuat Baik dan Silaturahim (Hadits Bulughul Maram) — Kamis, 1 Jumadilawal 1447 H, 23 Oktober 2025 @ GunungkidulMuhammad Abduh TuasikalArtikel Rumaysho.Com Tagsadab bersilaturahmi bahaya memutus silaturahim keutamaan silaturahim pentingnya silaturahim dalam islam silaturahim silaturahmi
فرج لا يخطر على بال
Oleh:
Syaikh Sya’ie Muhammad al-Ghubaisyi
أ. شائع محمد الغبيشي
يُصاب المسلم بالكرب والبلاء والمحنة، فيَعظُمُ الكربُ عليه، ويَبلغُ البلاء منتهاه، يتلفت حوله فلا يجد عند أحدٍ من البشر نجدةً أو مفزعًا، يلتفت يَمْنةً ويلتفت يَسْرةً، ينتقل من مكان إلى مكان، فلا يجد من ينجده أو يزيل كربته، أو يفرج همه، حتى أقرب الناس إليه، ويعذرهم؛ لأنه يعلم أن ذلك خارجٌ عن قدراتهم وإمكاناتهم، وكم يبلغ الهم والكرب بالعبد عندما لا يجد عند أقرب قريب وأحب حبيب من يزيل عنه ولو بعضًا مما يعانيه البلاء والكرب! حتى يبلغ الأمر بالعبد أن ييأس من الخلق جميعًا، وفجأةً وبالتفاتةٍ واحدةٍ وبكلماتٍ معدودةٍ يأتيه الفرج على غير بال، ومن حيث لا تحتسب، ويأتيه فوق ما يريد، وأعظم مما يريد
Seorang Muslim pasti pernah tertimpa musibah, ujian, dan cobaan, dan terkadang musibah itu terasa sangat berat baginya, dan cobaan itu sudah mencapai puncaknya. Namun, ketika dia menoleh di sekitarnya, tidak ada seorang pun manusia yang dapat memberinya pertolongan dan tempat mengadu. Dia menoleh kiri dan kanan, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi tidak ada juga yang mampu membantu atau mengangkat musibah itu, bahkan oleh orang terdekatnya.
Namun, dia tetap memaklumi mereka, karena dia mengetahui dengan pasti bahwa musibah itu di luar kemampuan dan kesanggupan mereka.
Betapa sering musibah dan cobaan menimpa seorang hamba hingga ke titik puncaknya, ketika dia tidak dapat lagi menemukan orang terdekat dan tercintanya yang mampu menghilangkan musibah itu meski hanya sebagian kecilnya, hingga hamba itu mencapai tingkat putus asa dari seluruh makhluk, tapi tiba-tiba dengan satu tengokan dan beberapa butir kata, solusi datang di luar perkiraan, dari arah yang tidak pernah diduga, bahkan melebihi apa yang dia inginkan.
فما هي هذه الكلمات المعدودات؟ وإلى من وجهها فجاءته هذه النجدة وذلك الفرج؟ تأمل هذا الخبر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: “حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: 173]”؛ رواه البخاري. وفي رواية: قال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: “كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل”؛ رواه البخاري.
Apa kiranya untaian kalimat yang diucapkan itu? Kepada siapa ia dihaturkan, sehingga menghadirkan pertolongan dan solusi yang demikian? Perhatikanlah hadis berikut ini.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: “Hasbunallahu wa ni’mal wakil, kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim Alaihissalam saat dilempar ke dalam api. Ini juga kalimat yang diucapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam ketika orang-orang berkata, ‘Sungguh orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, maka takutlah kepada mereka!’ Tapi ucapan itu menambah kuat iman mereka (kaum Muslimin) dan mereka menjawab: Hasbunallahu wa ni’mal wakil (Cukuplah Allah penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung).’ (QS. Ali Imran: 173).” (HR. Al-Bukhari).
Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Ucapan terakhir Nabi Ibrahim Alaihissalam saat dilempar ke dalam api adalah, ‘Hasbiyallahu wa ni’mal wakil!’” (HR. Al-Bukhari).
هذا خبر عجيب عظيم، وفيه من الفوائد والهدايات الكثير والكثير، منها:
أولًا: عظم البلاء الذي تعرض له نبي الله إبراهيم عليه السلام، وعظم توكله واعتماده على الله وتفويضه الأمر إليه، عاداه وأذاه كل من حولها حتى والده الذي خرج من صلبه، واجتمعوا كلهم على قتله بطريقة عجيبة، فيها من الظلم والعدوان والتشفِّي والنكاية والبغضاء والحقد الكثير والكثير، وإنك لتعجب أن أباه بين تلك الجموع وهو صابر محتسب ثابت على دينه ومبدئه، قال تعالى: ﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ * فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ [الصافات: 97، 98]، وقال سبحانه: ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: 68]
Ini merupakan hadis yang menakjubkan dan agung, di dalamnya terdapat banyak pelajaran dan petunjuk, di antaranya:
Pelajaran Pertama:
Besarnya ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim Alaihissalam, dan besarnya tawakal dan kebergantugan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan penyerahan segala urusan kepada-Nya. Di saat semua orang yang ada di sekitarnya – termasuk ayahnya yang beliau berasal dari tulang sulbinya – memusuhi dan menyakiti beliau. Mereka semua bersepakat untuk membunuhnya dengan cara yang di luar nalar, cara yang penuh dengan kezaliman, permusuhan, dendam, penyiksaan, kebencian, dan kedengkian.
Kamu pasti heran bahwa ayah beliau turut serta dalam golongan itu, sedangkan beliau tetap sabar dan teguh di atas agama dan prinsip beliau. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ * فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
“Mereka berkata, ‘Buatlah bangunan (perapian) untuk (membakar)-nya, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.’ Mereka bermaksud memperdayainya, (namun Allah menyelamatkannya), lalu Kami menjadikan mereka orang-orang yang hina.” (QS. Ash-Shaffat: 97-98). Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman:
قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ
“Mereka berkata, ‘Bakarlah dia (Ibrahim) dan bantulah tuhan-tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.’” (QS. Al-Anbiya: 68).
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الأحزاب عندما تحزب المشركون واليهود والمنافقون يريدون استئصالهم قال تعالى: ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا * وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الأحزاب: 10 – 12]، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت الصحابة رضي الله عنهم، وأخذ صلى الله عليه وسلم يبشِّرهم بالفتوح، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه: “عَرَضَ لَنَا صَخْرَةٌ فِي مَكَانٍ مِن الخَنْدَقِ لَا تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ، قَالَ: فَشَكَوْهَا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فجاء فأخذ المِعْوَلَ فقال: بسمِ اللهِ، فضرب ضربةً فكسر ثُلُثَها، وقال: اللهُ أكبرُ أُعْطِيتُ مَفاتيحَ الشامِ، واللهِ إني لَأُبْصِرُ قصورَها الحُمْرَ الساعةَ، ثم ضرب الثانيةَ فقطع الثلُثَ الآخَرَ، فقال: اللهُ أكبرُ، أُعْطِيتُ مفاتيحَ فارسٍ، واللهِ إني لَأُبْصِرُ قصرَ المدائنِ أبيضَ، ثم ضرب الثالثةَ وقال: بسمِ اللهِ، فقطع بَقِيَّةَ الحَجَرِ فقال: اللهُ أكبرُ أُعْطِيتُ مَفاتيحَ اليَمَنِ، واللهِ إني لَأُبْصِرُ أبوابَ صنعاءَ من مكاني هذا الساعةَ”؛ رواه الإمام أحمد[رواه الإمام أحمد وصححه ابن حجر في الفتح (7/ 397).].
Demikian juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam dan para sahabat beliau pada perang Ahzab, ketika kaum Musyrikin, Yahudi, dan Munafikin bersekutu untuk memberantas kaum Muslimin sepenuhnya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengisahkan:
إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا * وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا
“Ketika mereka datang kepadamu dari arah atas dan bawahmu, ketika penglihatanmu terpana, hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah, di situlah orang-orang mukmin diuji dan digoncangkan (hatinya) dengan guncangan yang dahsyat. (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit berkata, ‘Apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanyalah tipu daya belaka.’” (QS. Al-Ahzab: 10-12).
Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam tetap teguh, begitu juga dengan para sahabat. Ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam memberi kabar gembira berupa kemenangan. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib Radhiyallahu ‘anhu, ia menceritakan, “Ada batu besar yang merintangi kami dalam menggali parit, batu keras yang tidak mampu dipecah dengan pangkur. Kami lalu melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam, dan beliau pun mengambil pangkur lalu mengucapkan, ‘Bismillah!’ Beliau memukul satu kali, sehingga batu itu terpecah sepertiganya. Beliau lalu berseru, ‘Allahu Akbar! Aku dikaruniai kunci-kunci negeri Syam. Demi Allah! Sungguh aku melihat istana-istana merahnya saat ini!’ Kemudian beliau memukul batu itu sekali lagi, dan terpecahlah sepertiga lagi. Beliau lalu berseru, ‘Allahu Akbar! Aku dikaruniai kunci-kunci negeri Persia. Demi Allah! Sungguh aku melihat Istana Madain yang putih saat ini!’ Kemudian beliau memukul batu itu untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan, ‘Bismillah!’ Sehingga terpecahlah sisa batu itu, lalu berseru, ‘Allahu Akbar! Aku dikaruniai kunci-kunci negeri Yaman. Demi Allah! Sungguh aku melihat pintu-pintu kota Shan’a dari tempatku ini saat ini!’” (HR. Imam Ahmad. Dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari jilid 7 hlm. 397).
ثانيًا: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أعظم الخلق توكلًا على الله واعتمادًا عليه سبحانه، يفوضون أمورهم ويكلون شئونهم إليه سبحانه، وقد قال جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم: ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [إبراهيم: 12].
Pelajaran Kedua:
Para rasul merupakan makhluk-makhluk yang paling besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, mereka menyerahkan urusan mereka kepada-Nya. Semua rasul Alaihimussalam telah berkata kepada kaum mereka:
وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
“Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan kepada kami jalan-jalan (keselamatan)? Sungguh, kami benar-benar akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal seharusnya berserah diri.” (QS. Ibrahim: 12).
ثالثًا: أن من انتَصَرَ بِاللهِ نَصَرَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ، ومَن تَوكَّلَ على اللهِ فهوَ حَسبُه وكافيه، ومن كان الله حسبه، فممَّ يخاف؟! فما أحوجنا إلى أن نتوكل على الله حق التوكل، ونفوض أمورنا إليه سبحانه! قال ابن القيم رحمه الله: “هذه الكلمةُ العظيمةُ التوَكُّل على الله والاعتماد عليه والالتجاء إليه سبحانه، وأنَّ ذلك سبيلُ عِزِّ الإنسان ونَجاتِه وسلامته، قال ابنُ القيم رحمه الله: “وهو حَسْبُ من تَوَكَّل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمِّنُ خوفَ الخائف، ويُجيرُ المستجير، وهو نِعْم المولى ونعم النَّصير، فمَن تولَّاه واستنصرَ به، وتوكَّلَ عليه، وانقطعَ بكُلِّيَّته إليه، تولَّاه وحفظَه وحَرَسَهُ وصانَه، ومَن خافه واتَّقاه أمَّنَه مِمَّا يخافُ ويَحذَر، وجَلَبَ إليه كلَّ ما يحتاج إليه من المنافع”[بدائع الفوائد (2/ 763).].
Pelajaran Ketiga:
Siapa yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, pasti akan mendapat pertolongan-Nya, dan siapa yang bertawakal kepada-Nya, maka sungguh Dia sudah cukup baginya. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mencukupinya, lalu dari apa lagi dia akan takut?!
Betapa besar kebutuhan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan sebenar-benarnya dan menyerahkan urusan kita kepada-Nya! Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah berkata, “Ini merupakan kalimat yang sangat agung, bertawakal, bersandar, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Itu merupakan jalan kemuliaan, kemenangan, dan keselamatan manusia.” Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah juga menambahkan, “Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan cukup bagi orang yang bertawakal kepada-Nya, dan melindungi orang yang berserah diri kepada-Nya. Dialah yang memberi rasa aman terhadap ketakutan orang yang takut, melindungi orang yang meminta perlindungan, dan Dialah sebaik-baik pelindung dan penolong.
Barang siapa yang memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, bertawakal kepada-Nya, dan benar-benar memutus harapan kecuali dari-Nya, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan memberinya pertolongan, perlindungan, dan penjagaan.
Barang siapa yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka Dia akan memberinya rasa aman dari apa yang ia takuti dan mendatangkan kepadanya segala kebaikan yang ia butuhkan.” (Kitab Bada’iul Fawaid jilid 2 hlm. 763).
رابعًا: أن من توكَّل على الله وفوَّض أمره إليه، نصره بما لا يخطر على البال، تأمل كيف نصر الله إبراهيم عليه السلام ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ [الأنبياء: 68 – 70]، وتأمل كيف نصر الله رسوله يوم الأحزاب؛ أرسل الله ريحًا شديدة قلعت خيامهم، وجرفت مؤنهم، وأطفأت نيرانهم، فدَبَّ الهلع في نفوس المشركين، وفرُّوا هاربين إلى مكة، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: 9].
Pelajaran Keempat:
Siapa yang bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka Dia akan menolongnya dengan cara yang tidak terlintas dalam pikirannya. Renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala menolong Nabi Ibrahim Alaihissalam:
قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
“Mereka berkata, ‘Bakarlah dia (Ibrahim) dan bantulah tuhan-tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.’ Kami (Allah) berfirman, ‘Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim!’ Mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, tetapi Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.” (QS. Ibrahim: 68-70).
Perhatikan juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam pada perang Ahzab. Dia mengirim angin kencang yang menumbangkan kemah para musuh, menghempaskan barang-barang mereka, dan memadamkan api unggun mereka, sehingga ketakutan merasuk ke dalam jiwa kaum Musyrikin, dan membuat mereka berlarian kabur kembali ke Makkah. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا
“Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara (malaikat) yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ahzab: 9).
خامسًا: فضل التَّوكُّلِ الصَّادقِ على اللهِ تعالَى، وحُسنِ اللُّجوءِ إليه، وأنَّ فيه النَّجاةَ للعبد في الدنيا والآخرة لمن أخذ بالأسباب وبذل ما يستطيع منها، ثم توكَّل على الله، فإن الله يحفظه ويحميه ويكفيه ويصرف عنه السوء، ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: 3]، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: “إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟”؛ رواه الترمذي وصححه الألباني [سنن أبي داود (4/ 325).]، ومن توكل على الله حق التوكل رزقه من حيث لا يحتسب، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»؛ رواه الترمذي وصححه الألباني [سنن الترمذي (4/ 166).]، ابذل السبب وتوكل على الله، وفوض الأمر إليه، وكلُّك ثقة أنه سيهب لك ما لا يخطر لك على بال:
وتشاءُ أنت من البشائر قطرةً ويشاء ربُّك أن يُغيثك بالمطر
وتشاء أنت من الأماني نجمةً ويشاء ربُّك أن يُناولك القمر
وتشاء أنت من الحياة غنيمةً ويشاء ربُّك أن يسوقَ لك الدرر
Pelajaran Kelima:
Keutamaan tawakal yang tulus kepada allah Subhanahu Wa Ta’ala dan keseriusan memohon perlindungan kepada-Nya, dan ini semua dapat mendatangkan keselamatan manusia di dunia dan akhirat bagi mereka yang menyertakan ikhtiar dan usaha yang mungkin diusahakan, lalu bertawakal kepada-Nya. Dengan begitu, Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan menjaga, melindungi, dan mencukupinya, dan menghindarkan keburukan darinya.
“Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya.” (QS. At-Talaq: 3).
Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟
“Apabila seseorang keluar dari rumahnya dan mengucapkan: Bismillahi tawakkaltu ‘alallah laa haula wa laa quwwata illa billah (Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah), maka akan dikatakan kepadanya, ‘Kamu akan diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi.’ Sehingga setan-setan menyingkir darinya.
Lalu setan lain akan berkata, ‘Bagaimana kamu akan dapat mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?’” (HR. At-Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Juga disebutkan dalam Sunan Abi Daud jilid 4 hlm. 325).
Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan benar, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:
لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا
“Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti halnya burung yang diberi rezeki, yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar lalu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang.” (HR. At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi jilid 4 hlm. 166 dan disahihkan Al-Albani).
Kerahkanlah usaha, lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan serahkan hasilnya kepada-Nya, serta yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan mengaruniakan kepadamu sesuatu yang tidak terlintas dalam pikiranmu sebelumnya.
وَتَشَاءُ أَنْتَ مِنَ الْبَشَائِرِ قَطْرَةً وَيَشَاءُ رَبُّكَ أَنْ يُغِيْثَكَ بِالْمَطَرِ
Kamu ingin kabar gembira setetes saja
Sedangkan Tuhanmu ingin mengguyurmu dengan hujan
وَتَشَاءُ أَنْتَ مِنَ الْأَمَانِي نَجْمَةً وَيَشَاءُ رَبُّكَ أَنْ يُنَاوِلَكَ الْقَمَرَ
Kamu ingin dari cita-citamu mendapat satu bintang saja
Tapi Tuhan ingin memberimu bulan
وَتَشَاءُ أَنْتَ مِنَ الْحَيَاةِ غَنِيْمَةً وَيَشَاءُ رَبُّكَ أَنْ يَسُوقَ لَكَ الْدُرَرَ
Kamu ingin dalam hidupmu meraih harta sekedarnya saja
Tapi Tuhanmu hendak menghadirkan bagimu mutiara dan intan berlian
سادسًا: الحرص على دراسة سير الأنبياء وقصصهم فيه حث على تقوية الصلة بالله، والإقبال عليه ومحبته، والتوكل عليه، وفيه زيادة لإيمان العبد وثباته على الهدى، وفيها كثير من الدروس والعبر والمواعظ ﴿ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: 120].
Pelajaran Keenam:
Serius dalam mempelajari sejarah para Nabi dan kisah-kisah mereka dapat memberi dorongan untuk menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, senantiasa menghadap kepada-Nya, mencintai-Nya, dan bertawakal kepada-Nya. Juga dapat meningkatkan keimanan dan keteguhan di atas jalan petunjuk. Dalam kisah-kisah mereka terdapat banyak pelajaran, ibrah, dan pengingat.
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
“Semua kisah rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu (Nabi Muhammad), yaitu kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu (segala) kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang mukmin.” (QS. Hud: 120).
Sumber:
https://www.alukah.net/sharia/0/174525/فرج-لا-يخطر-على-بال/
Sumber artikel PDF
🔍 Cara Menghadiahkan Al Fatihah, Istri Yang Sabar, Pertanyaan Tauhid, Haid Sebulan 2x
Visited 180 times, 1 visit(s) today
Post Views: 320
<img class="aligncenter wp-image-43307" src="https://i0.wp.com/konsultasisyariah.com/wp-content/uploads/2023/10/qris-donasi-yufid-resized.jpeg" alt="QRIS donasi Yufid" width="741" height="1024" />
Laporan Produksi Yufid Bulan September 2025
Bismillahirrohmanirrohim…
Yayasan Yufid Network telah berkontribusi selama 15 tahun dalam menyediakan konten pendidikan dan dakwah Islam secara gratis melalui berbagai platform, termasuk channel YouTube seperti Yufid.TV, Yufid EDU, dan Yufid Kids yang telah memproduksi 23.594 video dengan total 6.829.119 subscribers. Yufid juga mengelola situs website dan telah mempublikasikan 10.089 artikel yang tersebar di berbagai platform.
Melalui laporan produktivitas ini, Yufid berusaha memberikan transparansi terhadap projek dan perkembangan tim, memperkuat keterlibatan pemirsa Yufid dan membangun wadah kreativitas bersama untuk penyebaran dakwah Islam.
Yufid telah menjadi kekuatan signifikan dalam memberikan akses luas kepada pengetahuan dan informasi dakwah Islam, mencapai lebih dari 929.039.785 views di platform YouTube. Dengan komitmen pada misi non-profit kami, Yufid terus memberikan dampak positif dan berusaha untuk terus berkembang sembari mempertahankan transparansi dan keterlibatan pemirsa yang kuat.
Channel YouTube YUFID.TV
<img decoding="async" src="https://yufid.org/wp-content/uploads/2025/10/image.png" alt="" class="wp-image-516"/>
Total Video Yufid.TV: 19.530 video
Total Subscribers: 4.185.784 subscribers
Total Tayangan Video: 735.202.178 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 111 video
Produksi Video September 2025: 101 video
Tayangan Video September 2025: 2.514.561 views
Waktu Tayang Video September 2025: 265.554 jam
Penambahan Subscribers September 2025: +5.610
Selama bulan September 2025 tim Yufid menyiarkan 129 video live.
Channel YouTube YUFID EDU
<img decoding="async" src="https://yufid.org/wp-content/uploads/2025/10/image-2.png" alt="" class="wp-image-518"/>
Total Video Yufid Edu: 3.087 video
Total Subscribers: 331.751
Total Tayangan Video: 22.790.706 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 21 video
Produksi Video September 2025: 36 video
Tayangan Video September 2025: 182.814 views
Waktu Tayang Video September 2025: 10.179 jam
Penambahan Subscribers September 2025: +1.789
Channel YouTube YUFID KIDS
<img decoding="async" src="https://yufid.org/wp-content/uploads/2025/10/image-4.png" alt="" class="wp-image-520"/>
Total Video Yufid Kids: 93 video
Total Subscribers: 537.479
Total Tayangan Video: 167.125.647 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 1 video
Produksi Video September 2025: 2 video
Tayangan Video September 2025: 1.761.781 views
Waktu Tayang Video September 2025: 87.615 jam
Penambahan Subscribers September 2025: +3.297
Untuk memproduksi video Yufid Kids membutuhkan waktu yang lebih panjang dan pekerjaan yang lebih kompleks, namun sejak awal produksi hingga video dipublikasikan tim tetap bekerja setiap harinya.
Channel YouTube Dunia Mengaji
Channel Dunia Mengaji adalah untuk menampung video-video yang secara kualitas pengambilan gambar dan kualitas gambar jauh di bawah standar Yufid.TV, agar konten dakwah tetap bisa dinikmati oleh pemirsa.
Total Video: 272
Total Subscribers: 5.001
Total Tayangan Video: 478.097 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 3 video
Tayangan Video September 2025: 898 views
Jam Tayang Video September 2025: 153 Jam
Penambahan Subscribers September 2025: 7
Channel YouTube العلم نور
Channel “Al-’Ilmu Nuurun” ini merupakan wadah yang berisi ceramah singkat maupun kajian-kajian panjang dari Masyayikh dari Timur Tengah seperti Syaikh Sulaiman Ar-Ruhayli, Syaikh Utsman Al-Khomis, Syaikh Abdurrazaq bin Abdulmuhsin Al Badr hafidzahumullah dan masih banyak yang lainnya yang full menggunakan bahasa Arab. Cocok disimak para pemirsa Yufid.TV yang sudah menguasai bahasa Arab serta ingin belajar bersama guru-guru kita para alim ulama dari Saudi dan sekitarnya.
Total Video: 612
Total Subscribers: 57.200
Total Tayangan Video: 3.443.157 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 8 video
Produksi Video September 2025: 0 video
Tayangan Video September 2025: 32.464 views
Penambahan Subscribers September 2025: +300
Instagram Yufid TV & Instagram Yufid Network
<img decoding="async" src="https://yufid.org/wp-content/uploads/2025/10/image-3.png" alt="" class="wp-image-519"/>
Instagram Yufid.TV
Total Konten: 4.691 Postingan
Total Pengikut: 1.192.222 followers
Konten Bulan September 2025: 50
Views Konten September: 2.192.195 views
Rata-Rata Produksi: 47 konten/bulan
Penambahan Followers September 2025: +8.373
Instagram Yufid Network
Total Konten: 4.603 Postingan
Total Pengikut: 519.682
Konten Bulan September 2025: 50
Views Konten September: 19.353 views
Rata-Rata Produksi: 47 konten/bulan
Penambahan Followers September 2025: +3.286
Pertama kali Yufid memanfaatkan media instagram memiliki nama Yufid Network yaitu sejak tahun 2013, sebelum akhirnya di buatlah akun Yufid.TV pada tahun 2015 agar lebih dikenal seiring dengan berkembangnya channel YouTube Yufid.TV.
Video Nasehat Ulama
Salah satu project yang dikerjakan oleh tim Yufid.TV yaitu video Nasehat Ulama. Video pendek namun penuh dengan faedah berisi penggalan-penggalan nasehat serta jawaban dari pertanyaan kaum muslimin yang disampaikan ulama-ulama terkemuka.
<img decoding="async" src="https://yufid.org/wp-content/uploads/2025/10/image-5.png" alt="" class="wp-image-521"/>Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, konten Nasehat Ulama di channel YouTube Yufid.TV telah mempublikasikan 25 video.
Nasehat Ulama juga membuat konten baru dengan konsep berbeda dengan tetap mengambil penggalan-penggalan nasehat para masyaikh berbahasa Arab dalam bentuk shorts YouTube dan reels Instagram.
Video Motion Graphic & Yufid Kids
Project unggulan lainnya dari Yufid.TV yaitu pembuatan video animasi motion graphic dan video Yufid Kids. Project motion graphic Yufid.TV memproduksi video-video berkualitas yang memadukan antara pemilihan tema yang tepat berupa potongan-potongan nasehat dari para ustadz atau ceramah-ceramah pendek yang diilustrasikan dalam bentuk animasi yang menarik. Sedangkan video Yufid Kids mengemas materi-materi pendidikan untuk anak yang disajikan dengan gambar animasi anak sehingga membuat anak-anak kita lebih bersemangat dalam mempelajarinya.
<img decoding="async" src="https://yufid.org/wp-content/uploads/2025/10/image-1.png" alt="" class="wp-image-517"/>Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, konten Motion Graphics di channel YouTube Yufid.TV telah mempublikasikan 3 video.
Untuk memproduksi video Motion Graphic dan Yufid Kids membutuhkan waktu yang lebih panjang dan pekerjaan yang lebih kompleks, namun sejak awal produksi hingga video dipublikasikan tim tetap bekerja setiap harinya.
Website KonsultasiSyariah.com
KonsultasiSyariah.com merupakan sebuah website yang menyajikan berbagai tanya jawab seputar permasalahan agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kasus dan jawaban dipaparkan secara jelas dan ilmiah, berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta keterangan para ulama. Hingga saat ini, website tersebut telah menuliskan 5.141 artikel yang berisi materi-materi permasalahan agama yang telah dijawab oleh para asatidz. Artikel dalam website KonsultasiSyariah.com juga kami tuangkan ke dalam bentuk audio visual dengan teknik typography dan dibantu oleh pengisi suara (voice over) yang telah memproduksi 2.025 audio dan rata-rata menghasilkan 23 audio per bulan yang siap dimasukkan ke dalam project video Poster Dakwah Yufid.TV.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website KonsultasiSyariah.com telah mempublikasikan 8 artikel.
Website KisahMuslim.com
KisahMuslim.com berisi kumpulan kisah para Nabi dan Rasul, kisah para sahabat Nabi, kisah orang-orang shalih terdahulu, biografi ulama, dan berbagai kisah yang penuh hikmah. Dalam website tersebut sudah ada 1.139 artikel yang banyak kita ambil pelajarannya.
Artikel dalam website KisahMuslim.com juga kami tuangkan ke dalam bentuk Audio Visual dengan teknik typography serta ilustrasi yang menarik dengan dibantu oleh pengisi suara (voice over) yang telah memproduksi 710 audio dan rata-rata menghasilkan 16 audio per bulan yang siap dimasukkan ke dalam project video Kisah Muslim Yufid.TV.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website KisahMuslim.com telah mempublikasikan 3 artikel.
Website KhotbahJumat.com
KhotbahJumat.com berisi materi-materi khutbah yang bisa kita gunakan untuk mengisi khotbah pada ibadah shalat Jumat, terdapat 1.304 artikel hingga saat ini, yang sangat bermanfaat untuk para khatib dan da’i yang mengisi khutbah jumat.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website KhotbahJumat.com telah mempublikasikan 2 artikel.
Website PengusahaMuslim.com
PengusahaMuslim.com merupakan sebuah website yang mengupas seluk beluk dunia usaha dan bisnis guna membantu terbentuknya pengusaha muslim baik secara ekonomi maupun agamanya, yang pada akhirnya menjadi kesatuan kuat dalam memperjuangkan kemaslahatan umat Islam dan memajukan perekonomian Indonesia. Terdapat 2.506 artikel dalam website tersebut yang dapat membantu Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses, tidak hanya di dunia, namun kesuksesan tersebut abadi hingga ke negeri akhirat.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website PengusahaMuslim.com telah mempublikasikan 1 artikel.
*Tim artikel Yufid yang terdiri dari penulis, penerjemah, editor, dan admin website menyiapkan konten untuk seluruh website yang dikelola oleh Yufid secara bergantian.
Website Kajian.net
Kajian.net adalah situs koleksi audio ceramah berbahasa Indonesia terlengkap dari ustadz-ustadz Ahlussunnah wal Jamaah, audio bacaan doa dan hadits berformat mp3, serta software islami dan e-Book kitab-kitab para ulama besar.
Total audio yang tersedia dalam website kajian.net yaitu 34.566 file mp3 dengan total ukuran 487 Gb dan pada bulan September 2025 ini telah mempublikasikan 529 file mp3.
Website Kajian.net bercita-cita sebagai gudang podcast kumpulan audio MP3 ceramah terlengkap yang dapat di download secara gratis dengan harapan dapat memudahkan Anda belajar hukum agama Islam dan aqidah Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafush sholeh. Kami juga rutin mengupload audio MP3 seluruh kajian Yufid ke platform SoundCloud, Anda dapat mengaksesnya melalui https://soundcloud.com/kajiannet, yang pada bulan September 2025 ini saja telah didengarkan 14.837 kali dan telah di download sebanyak 190 file audio.
Project Terjemahan
Project ini bertujuan menerjemahkan konten dakwah, baik itu artikel, buku, dan ceramah para ulama. Konten dakwah yang aslinya berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, konten yang sudah diterjemahkan tersebut diolah kembali menjadi konten video, mp3, e-book, dan artikel di website. Sejak memulai project ini pada tahun 2018, tim penerjemah Yufid telah menerjemahkan 4.489.627 kata dengan rata-rata produksi per bulan 53.447 kata.
Dalam 1 bulan terakhir yaitu bulan September 2025, project terjemahan ini telah menerjemahkan 49.019 kata.
Perekaman Artikel Menjadi Audio
Program ini adalah merekam seluruh artikel yang dipublikasikan di website-website Yufid seperti KonsultasiSyariah.com, PengusahaMuslim.com dan KisahMuslim.com ke dalam bentuk audio. Program ini bertujuan untuk memudahkan kaum muslimin mengakses konten dakwah dalam bentuk audio, terutama bagi mereka yang sibuk sehingga tidak ada kesempatan untuk membaca artikel. Mereka dapat mendengarkan audio yang sudah Yufid rekam sambil mereka beraktivitas, semisal di kendaraan, sambil bekerja, berolahraga, dan lain-lain.
Total artikel yang sudah direkam dalam format audio sejak pertama dimulai program ini tahun 2017 yaitu 2.761 artikel dengan total durasi audio 262 jam dengan rata-rata perekaman 28 artikel per bulan.
Dalam 1 bulan terakhir yaitu bulan September 2025, perekaman audio yang telah diproduksi yaitu 18 artikel.
Pengelolaan Server
Yufid mengelola tujuh server yang di dalamnya berisi website-website dakwah, ada server khusus untuk website Yufid, website yang telah dijelaskan pada point-point diatas hanya sebagian kecil dari website yang kami kelola, yaitu bertotal 29 website dalam satu server tersebut. Selain itu terdapat juga website para ulama yang diletakkan di server yang berbeda dari server Yufid, ada pula website-website dakwah, streaming radio dll. Dari ketujuh server yang Yufid kelola kurang lebih terdapat 107 website yang masih aktif hingga saat ini.
Demikian telah kami sampaikan laporan produksi Yufid Network pada bulan September 2025.
Wallahu a’lam… Washallallahu ‘ala Nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa sahbihi ajma’in, walhamdulillahi rabbil ‘alamin.
🔍 Cara Menghadiahkan Al Fatihah, Istri Yang Sabar, Pertanyaan Tauhid, Haid Sebulan 2x
Visited 29 times, 1 visit(s) today
Post Views: 323
<img class="aligncenter wp-image-43307" src="https://i0.wp.com/konsultasisyariah.com/wp-content/uploads/2023/10/qris-donasi-yufid-resized.jpeg" alt="QRIS donasi Yufid" width="741" height="1024" />
Daftar Isi
ToggleMengambil hikmah penegakan hukuman hadd dari Maiz bin MalikHikmah yang lebih besar: Mencegah tersebarnya keburukanHukuman hadd adalah bentuk menjaga hak Allah ﷻPenegakan hukuman hadd menampilkan ketegasan dan kelembutan syariatHukuman hadd menolong pelakunyaSyariat Islam memiliki ragam bentuk pengaplikasian dalam merespon kondisi umat. Mulai dari himbauan penuh kelembutan hingga hukuman yang bersifat tegas. Semua bentuk syariat ini memiliki hikmah untuk perbaikan umat manusia. Imam Al ‘Izz bin Abdissalam rahimahullah berkata,إن الشريعة كلها مصالح؛ إمَّا درء مفاسد، أو جلب مصالح“Sesungguhnya seluruh syariat adalah untuk tujuan maslahat, baik dalam bentuk menolak mafsadat (keburukan) ataupun meraih mashlahat (kebaikan).” (Al-Qawaid, 1: 9; dalam Ushul Dakwah, hal. 301) [1]Dakwah yang berisi ilmu yang jelas beserta penyampaian yang lemah-lembut ditujukan untuk mengajak manusia ke jalan kebaikan. Namun, tumpuan Islam tidak hanya kepada dakwah yang lemah-lembut. Dalam Islam, kehangatan dakwah tersebut disertai dengan ketegasan dalam sistem hukumnya.Hukum hadd [2] dan ta’zir yang ditetapkan dalam konteks syariat Islam, pada perspektif sebagian orang di masa kini terkesan keras sekali. Hal ini karena penilaiannya ditinjau pada bentuk hukumannya yang fisikal, seperti potong tangan bahkan penyembelihan. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis akan menguraikan perspektif lain dari penegakan hukuman -khususnya hadd- dalam Islam yang membawa rahmat dalam praktiknya.Mengambil hikmah penegakan hukuman hadd dari Maiz bin MalikSalah satu sahabat yang pernah terjatuh dalam dosa besar adalah Maiz bin Malik radhiyallahu ‘anhu. Beliau pernah berzina dengan salah satu wanita dalam tanggungan Hazzal Al-Aslami radhiyallahu ‘anhu. Maiz sangat bingung atas dosa yang ia lakukan tatkala seluruh kaum muslimin berangkat berjihad. Akhirnya, beliau melapor kepada Hazzal sang Tuan, lalu Hazzal menyarankan untuk mencari solusi kepada Nabi ﷺ. Akhirnya, setelah Rasulullah ﷺ berusaha berpaling dari persaksian itu, mau tidak mau Rasulullah menegakkan hukuman hadd atasnya.Pada malam hari setelah hukum hadd ditegakkan kepada Maiz, Rasulullah ﷺ berkhotbah di hadapan kaum muslimin tentang apa hikmah dari kejadian ini.قال رسول الله ﷺ في خطبته: أَوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ !! عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَلْتُ بِهِRasulullah ﷺ berkata dalam khotbahnya, “Mengapa ketika kami berangkat berjihad di jalan Allah, salah seorang dari kalian ada yang tidak ikut berangkat dan bersama keluarga kami, ia memiliki desahan seperti kambing jantan (saat kawin). Maka tidaklah kalian menghadapkan kepadaku orang yang melakukan perbuatan itu melainkan aku akan memberinya sanksi.” (HR. Muslim no. 1694, terjemahan disandarkan kepada “Nabi Sang Penyayang” cet. Al-Kautsar, hal. 212)Isi khotbah beliau mengajak umat untuk menyelaraskan akal dan perasaan. Bagaimana jika dalam keadaan seluruh orang berjuang, tetapi ada salah satu dari kelompok tersebut yang berkhianat, yakni berzina dengan salah satu keluarga pejuang tersebut? Hal ini yang menjadi konteks Maiz saat berzina. Pada saat itu, orang-orang keluar berperang sementara Maiz berzina dengan budaknya Hazzal. [3]Hikmah yang lebih besar: Mencegah tersebarnya keburukanMaka, bayangkanlah keburukan yang dapat tersebar dengan tidak ditegakkannya hukuman hadd! Sebuah momen perjuangan di jalan Allah ﷻ yang mulia dimanfaatkan oleh seseorang untuk berkhianat bermaksiat kepada Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ jelaskan bahwa hal ini bisa terjadi kepada siapa saja. Bahkan korbannya pun bisa siapa saja dan dari keluarga siapapun. Tentu seorang manusia yang berakal akan marah jika keluarganya dinodai!Saat seseorang berzina, ia telah menodai kehormatan banyak pihak. Ia telah kehilangan akal kemanusiaannya, sehingga sudah berlaku layaknya hewan. Karena itulah, permisalan Nabi ﷺ dalam khotbah tersebut adalah “layaknya desahan kambing”. Selain karena ketepatan permisalan, juga karena hinanya perilaku tersebut.Hukuman hadd ditegakkan juga agar terjaga keadilan yang lebih luas. Saat seseorang berzina, ia telah menodai kehormatan banyak pihak. Jika tidak dihukum, maka betapa banyak hak orang yang tidak ditegakkan? Belum lagi dampaknya ketika hukum hadd tidak ditegakkan karena alasan pelakunya sudah tobat, misalnya, maka orang-orang akan menyepelekan perkara ini. Akan muncul pemikiran, “Tidak apa-apa berzina, tidak apa-apa orang lain tahu, yang penting aku bertobat!” Hal ini akan merusak tatanan moral masyarakat.Sebagaimana Nabi ﷺ memberikan pernyataan tegas di akhir khotbahnya, bahwa yang berzina semisal Maiz akan tetap dirajam sampai mati. Tujuannya adalah agar mencegah umat secara umum dari perbuatan ini. Adapun praktiknya ketika kasusnya benar-benar terjadi, terbukti Rasulullah ﷺ mengedepankan pengampunan dan tidak mau tahu dengan maksiat yang dilakukan pribadi tersebut.Hukuman hadd adalah bentuk menjaga hak Allah ﷻTidak hanya hak manusia yang ternodai, asalnya hak Allah ﷻ yang pertama kali ternodai saat seseorang bermaksiat. Oleh sebab itu, Allah menentukan langsung bentuk hukuman hadd bagi pelaku maksiat zina. Maka, penegakan hukuman hadd adalah bentuk penjagaan terhadap hak Allah ﷻ.Sebagaimana yang kita ketahui, hak Allah ﷻ jauh lebih utama dibandingkan hak manusia. Namun, terdapat pertimbangan rahmat kepada pelaku, sehingga dalam praktiknya, Nabi ﷺ tidak langsung menghukum Maiz. Nabi ﷺ berulang kali beralih dari persaksian Maiz. Tujuannya adalah:Agar persaksiannya kokoh dan tegak sebagai hujjah dalam menghukum;Menyelamatkan pelaku dari hukuman dan mencukupkan dengan tobat kepada Allah ﷻ.Akan tetapi, dalam konteks Maiz, beliau berulang kali menekankan persaksiannya sehingga persaksiannya sudah kokoh, keteguhan hatinya untuk dihukum besar, serta sudah diketahui oleh umat.Penegakan hukuman hadd menampilkan ketegasan dan kelembutan syariatSikap Nabi ﷺ ini mengandung hikmah yang luas, menunjukkan keseimbangan dalam ketegasan dan kelembutan. Keadaan seseorang bermaksiat dan menyimpan untuk dirinya sendiri tidak akan berdampak luas secara langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, Nabi ﷺ mendorong seseorang untuk menutupi aibnya.Adapun ketika maksiat itu sudah terangkat di depan hakim seperti Nabi ﷺ atau tersebar luas di masyarakat, terdapat dampak besar, yakni:Timbulnya gonjang-ganjing di masyarakat;Terhinanya pelaku;Beratnya hukuman hadd yang akan menimpa pelaku.Ketahuilah, tujuan utama syariat Islam bukanlah untuk menghukum manusia. Namun, untuk melahirkan kedamaian dan ketentraman dengan mencegah dari perbuatan buruk, sebab ancamannya teramat berat. Atas dasar inilah, syariat Islam dalam praktiknya begitu mendetail dalam penetapannya, mengedepankan rahmat dan kasih sayang dalam putusannya, serta berimbang (wasath) juga hikmah dalam penerapannya.Hukuman hadd menolong pelakunyaSelain itu, hukuman hadd yang ditegakkan akan menolong pelakunya di dunia dan akhirat. Karena hukuman hadd akan menjadi tiang pancang pertobatannya di hadapan Allah ﷻ. Hukuman hadd yang ditegakkan juga akan menjadi bukti di hadapan manusia bahwa pelaku telah menerima hukuman, maka tidak ada lagi peluang bagi manusia untuk mencelanya. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ﷺ setelah merajam Maiz dan wanita Ghamidiyah.Ketika Maiz dirajam, beliau akhirnya berusaha lari karena tidak kuat. Namun, ada seorang yang melemparkan tulang kepadanya hingga akhirnya terjatuh dan wafat. Nabi ﷺ pun bersabda,هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْ“Mengapa kalian tidak membiarkannya, siapa tahu ia bertobat dan Allah menerima tobatnya.” (HR. Abu Dawud no. 4419 dinilai hasan)Adapun ketika wanita Ghamidiyah yang mengakui perzinahannya, kemudian hukum hadd ditegakkan kepadanya, lalu Khalid bin Walid melampaui batas dalam merajamnya yang disertai laknat. Nabi ﷺ pun menasihatinya,فقال: مهْلًا يا خالدُ، فوالذي نَفْسي بيَدِه لقد تابتْ تَوبةً لو تابَها صاحبُ مَكْسٍ لغفَرَ اللهُ له. ثمَّ أمَرَ بها فصلَّى عليها، ودُفِنتْ“Lemah lembutlah, wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, ia telah bertobat dengan tobat yang seandainya seorang pemungut pajak bertobat seperti itu, niscaya Allah akan mengampuninya.” Kemudian beliau memerintahkan agar jenazahnya disalatkan, dan ia pun dimakamkan. (HR. Muslim no. 1695)Riwayat-riwayat ini sangat jelas menunjukkan tujuan utama dari penegakan hukuman syariat adalah rahmat kepada semuanya tanpa mengorbankan keadilan. Bukanlah tujuan dari penegakan hukum hadd adalah sekadar menghukum pelaku. Realita praktiknya, justru Nabi ﷺ sangat menghindari menghukum seseorang tanpa ada maslahat yang jelas. Banyak argumentasi lain yang menunjukkan bahwa hukum hadd tujuannya bukanlah menghukum, tetapi menegakkan keadilan dan rahmat di tengah umat manusia. Ragam riwayat ini hendaknya dibaca oleh para liberalis dan penentang tegaknya hukuman syariat.Baca juga: Tidak Ada Pertentangan (Kontradiksi) dalam Syariat Islam***Penulis: Glenshah FauziArtikel Muslim.or.id Referensi:Ar-Rahmah fi Hayati Rasulillah, hal. 116; karya Prof. Dr. Raghib As-Sirjani.Nabi Sang Penyayang, cet. Al-Kautsar, hal. 212.Rujukan hadis nasihat kepada Khalid bin Walid: https://dorar.net/hadith/sharh/132502Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syaikh Ahmad Hutaibah (6: 12): https://shamela.ws/book/36997/51Kitab Ushul Ad-Dakwah karya Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan: https://shamela.ws/book/22615/299Ragam referensi riwayat dapat dilihat dalam Bab Rajam dalam kitab hadis Shahih Muslim dan Sunan Abu Dawud. Terdapat riwayat Jabir bin Samurah, Abu Hurairah, dan Ibnu Buraidah dalam kisah ini. Namun, tidak disebutkan semuanya dalam rangka meringkas artikel. Catatan kaki:[1] Kitab Ushul Ad-Dakwah, karya Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan.[2] Hukum hadd adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah ﷻ kepada pelaku pidana dalam konteks hukum Islam yang telah termaktub spesifik pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.[3] Keterangan ini didapatkan dari Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Ahmad Hutaibah (6: 12). Semoga Allah ﷻ mengampuni kami dari kesalahan pemahaman.
Pertanyaannya berbunyi: “Apa makna hadis: ‘Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk-Nya?’ Apakah kata ganti dalam frasa “bentuk-Nya” boleh merujuk kepada lafaz Allah? Bagaimana pemahaman yang benar menurut Ahlus Sunnah?”
Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan ulama lainnya. “Jika salah seorang di antara kalian memukul, hindarilah memukul wajah, karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk-Nya.” Namun, riwayat yang lebih kuat menyebutkan: “dalam bentuk Ar-Rahman,” sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ulama lainnya: “…dalam bentuk Ar-Rahman.”
Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa bentuk Adam menyerupai bentuk Allah. Adam memiliki bentuk tersendiri, sedangkan Allah memiliki bentuk yang layak bagi-Nya. Maksud “bentuk-Nya” dalam hadis ini adalah sifat-sifat seperti mendengar, melihat, dan berbicara. Bukan berarti bentuk Allah serupa dengan bentuk makhluk-Nya. Kita wajib mensucikan Allah dari segala bentuk yang menyerupai makhluk.
Sebagaimana kita katakan: Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, memiliki wajah, memiliki tangan, dan memiliki jari-jari, tapi tidak seperti jari, tangan, atau wajah kita. Allah Ta’ala Maha Suci dari keserupaan dengan makhluk-Nya.
Demikian pula “bentuk-Nya” tidak menyerupai bentuk kita. Allah berfirman: “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. Asy-Syura: 11). Makna ini telah ditegaskan oleh Imam para imam: Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah—semoga Allah merahmatinya—dan beliau memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dalam bab tauhid. Demikian pula ulama-ulama lainnya telah menjelaskan hal ini tanpa ada yang mengingkarinya, dan tidak pula terdapat keraguan di dalamnya. Yang dimaksud adalah bentuk yang layak bagi Allah, yang sama sekali tidak menyerupai bentuk makhluk-Nya.
Sebagaimana wajah-Nya, tangan-Nya, jari-jari-Nya, keridhaan-Nya, dan kemurkaan-Nya, semuanya benar adanya, tapi tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk-Nya. “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.” Ini satu kesatuan pembahasan. Adapun anggapan bahwa Allah berbentuk seperti Adam, atau bahwa “Allah menciptakan Adam dalam bentuk-Nya” lalu disimpulkan bahwa bentuk Allah seperti manusia, maka semua perkataan ini tertolak. Begitu pula anggapan bahwa Allah berbentuk seperti makhluk, maka perkataan ini tidak dapat diterima.
Yang dimaksud dengan “dalam bentuk-Nya”—Subhanahu wa Ta’ala—adalah bahwa Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah berbicara, memiliki wajah, memiliki tangan, dan memiliki jari-jari. Namun dari sini tidak boleh disimpulkan bahwa bentuk-Nya menyerupai bentuk makhluk. Allah telah memberi kabar kepada kita, sekaligus menafikan keserupaan. Allah memberi tahu kita bahwa Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat, bahwa Dia berbicara, meridhai, dan memurkai, bahwa Dia memiliki wajah dan memiliki dua tangan. Kemudian Dia berfirman: “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya.” (QS. Asy-Syura: 11). “Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya.” (QS. Al-Ikhlas: 4). “Maka janganlah kalian membuat perumpamaan bagi Allah.” (QS. An-Nahl: 74).
Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menjelaskan kebenaran kepada kita. Maka, kewajiban kita adalah mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, lalu berhenti di situ dan berpegang teguh padanya. Walhamdulillah.
=====
السُّؤَالُ يَقُولُ مَا مَعْنَى حَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ؟ وَهَلْ يَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ الضَّمِيرُ فِي صُورَتِهِ إِلَى لَفْظِ الْجَلَالَةِ؟ مَا هُوَ الْوَجْهُ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ؟
حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدمَ عَلَى صُورَتِهِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَلَى صُوْرَةِ الرَّحْمَنُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ صُورَةُ الرَّحْمَنِ
وَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يُشْبِهُهُ هَذَا لَهُ صُورَةٌ وَهَذَا لَهُ صُورَةٌ صُورَتُه يَعْنِي سَمِيْعاً بَصِيْراً مُتَكَلِّماً مَا هُوَ مَعْنَى مِثْلِ الصُّورَةِ مِثْلَ غَيْرِهَا يَجِبُ النَّزْهَ لِلَّهِ عَنْ وَجْهِ غَيْرِاللَّهِ
كَمَا نَقُولُ سَمِيعٌ وَبَصِيرٌ وَلَهُ وَجْهٌ وَلَهُ يَدٌ وَلَهُ أَصَابِعُ لَيْسَ مِثْلَ أَصَابِعِنَا وَلَا أَيْدِينَا وَلَا وُجُوهِنَا فَاللَّهُ تَعَالَى يَتَقَدَّسُ عَنْ مُشَابَهَةِ خَلْقِهِ
فَهَكَذَا الصُّورَةُ لَيْسَ مِثْلَ صُوَرِنَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَقَد نَصَرَ هَذَا الْأَمْرَ بِالمَعْنَى إِمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاعْتَنَى بِهَذَا الْمَوْضُوْعِ فِي بَابِ التَّوْحِيدِ وَهَكَذَا آخَرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيِّنُوا هُنَا لَا إِنْكَارَ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ فِيهِ بَلْ هِيَ صُورَةُ تَلِيقُ بِاللَّهِ لَا يُشَابِهُ صُوْرَةَ خَلْقِهِ
كَمَا أَنَّ وَجْهَهُ وَيَدَهُ وَأَصَابِعَهُ وَرِضَاهُ وَغَضَبَهُ كُلَّهَا حَقٌّ لَا تُشَابِهُ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْبابُ وَاحِدٌ أَمًّا هُوَ فِي صُوْرَةِ آدَمَ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ هَذَا كَلَامُهُ كُلُّهُ مَرْدُوْدٌ أَوْ عَلَى صُوْرَةِ مَخْلُوْقٍ هَذَا كَلَامُهُ مَرْدُوْدٌ
وَالْمُرَادُ عَلَى صُورَتِهِ سُبْحَانَه يَعْنِي سَمِيْعاً بَصِيْراً مُتَكَلِّماً ذَا وَجْهٍ ذَا يَدٍ ذَا أَصَابِعَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا ثُمَّ أَنْ تَقُوْلَ هَذِهِ مُشَابِهَةٌ لِهَذِهِ فَقَدْ أَخْبَرَنَا وَقَدْ نَفَى أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِيعٌ وَأَنَّه بَصِيرٌ وَأَنَّه يَتَكَلَّم وَأَنَّه يَرْضَى وَأَنَّه يَغْضَبُ وَأَنَّ لَهُ وَجْهاً وَإِنَّ لَهُ يَدَيْنِ ثُمَّ بَعْدَهَا قَالَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ
فَقَدْ بَيَّنَ لَنَا الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَعَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ مَا قَالَ وَلَكِنْ هُنَا قِفْ مُمْسِكٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
Setiap amal saleh yang dilakukan seorang hamba tidak akan sia-sia di sisi Allah. Bahkan amal sekecil apa pun akan mendapat balasan dan dapat memberatkan timbangan kebaikan pada Hari Kiamat. Dalam banyak hadits, Rasulullah ﷺ menyebut beberapa amalan khusus yang memiliki bobot luar biasa di timbangan amal seorang mukmin.Penting untuk diketahui bahwa setiap amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah sesuatu yang Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikannya pada Hari Kiamat. Allah Ta‘ala berfirman:إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا“Sungguh, Allah tidak menzalimi seseorang walaupun seberat zarrah (debu yang sangat kecil). Jika ada kebaikan sebesar itu, niscaya Allah melipatgandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.” (QS. An-Nisā’: 40)Dan Allah juga berfirman:فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, ia pasti akan melihat (balasannya). Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, ia juga pasti akan melihat (balasannya).” (QS. Az-Zalzalah: 7–8)Namun, dalam berbagai nash (teks dalil) disebutkan bahwa ada amal-amal tertentu yang memiliki keistimewaan khusus: amal-amal tersebut secara khusus akan memberatkan timbangan amal kebaikan seseorang di akhirat kelak. Di antara amal-amal itu adalah: 1. Ucapan “Lā ilāha illallāh” (Kalimat Tauhid)Ucapan ini adalah hal paling berat dalam timbangan.Diriwayatkan dari ‘Abdullāh bin ‘Amr bin al-‘Āsh, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:( إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ )“Sesungguhnya Allah akan memisahkan seorang lelaki dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada Hari Kiamat. Lalu dibentangkan kepadanya sembilan puluh sembilan catatan amal, setiap catatan sepanjang mata memandang. Allah bertanya, ‘Apakah engkau mengingkari sesuatu dari semua ini? Apakah para malaikat pencatat-Ku menzalimimu?’ Ia menjawab, ‘Tidak, wahai Rabb-ku.’ Allah berkata, ‘Apakah engkau punya alasan?’ Ia menjawab, ‘Tidak, wahai Rabb-ku.’ Maka Allah berfirman, ‘Sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi Kami. Hari ini engkau tidak akan dizalimi.’ Lalu dikeluarkanlah sebuah kartu yang tertulis di dalamnya: Asyhadu allā ilāha illallāh wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasūluh. Allah berfirman, ‘Timbangkanlah kartu ini dengan catatan-catatan amalnya!’ Lelaki itu berkata, ‘Ya Rabb, apa arti kartu kecil ini dibandingkan catatan-catatan sebesar itu?’ Allah menjawab, ‘Engkau tidak akan dizalimi.’ Maka ditaruhlah catatan-catatan di satu sisi timbangan dan kartu tauhid di sisi lain. Ternyata catatan-catatan itu menjadi ringan dan kartu itu menjadi berat, sebab tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah.” (HR. Ahmad no. 6699, at-Tirmidzi no. 2639; dinyatakan sahih oleh Syaikh al-Albani) 2. Dzikir kepada Allah: Tasbih, Tahmid, Tahlil, dan TakbirDari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi ﷺ bersabda: “Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman:سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (Maha Suci Allah Yang Maha Agung, Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya).” (HR. al-Bukhari no. 6406, Muslim no. 2694)Dan dari Juwairiyah, istri Nabi ﷺ, bahwa Nabi keluar dari sisinya pada waktu pagi setelah salat Subuh, sementara beliau sedang duduk berzikir. Nabi ﷺ kembali setelah matahari meninggi, dan mendapati Juwairiyah masih dalam keadaan yang sama. Beliau bertanya, “Apakah engkau masih seperti keadaan ketika aku meninggalkanmu tadi?” Ia menjawab, “Ya.”Nabi ﷺ bersabda: “Sungguh, aku telah mengucapkan empat kalimat sebanyak tiga kali yang jika ditimbang dengan semua yang engkau ucapkan sejak pagi ini, maka empat kalimat itu lebih berat:سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ(Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya sebanyak jumlah makhluk-Nya, sesuai keridaan diri-Nya, seberat Arasy-Nya, dan sebanyak tinta kalimat-Nya).” (HR. Muslim no. 2726) 3. Menjaga Dzikir Setelah Shalat FardhuDari ‘Abdullāh bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhuma, Nabi ﷺ bersabda: خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ..)“Ada dua kebiasaan yang tidak dijaga oleh seorang muslim kecuali ia akan masuk surga. Keduanya ringan, tetapi sedikit yang melakukannya:(1) Bertasbih sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali, dan bertakbir sepuluh kali setiap selesai shalat. Itu berarti 150 kali di lisan dan 1500 kali di timbangan.(2) Bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali, dan bertasbih 33 kali ketika hendak tidur. Itu 100 kali di lisan dan 1000 kali di timbangan…” (HR. Ahmad no. 6616, Abu Dawud no. 5065, at-Tirmidzi no. 3410, an-Nasa’i no. 1331, Ibnu Majah no. 926; disahihkan oleh al-Albani dalam Shahih at-Targhib wat-Tarhib)4. Sabar dan Mengharap Pahala atas Wafatnya Anak yang SalehDari Zaid, dari Abi Salam, dari maula Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:( بَخٍ بَخٍ خَمْسٌ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدَاهُ وَقَالَ بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُسْتَيْقِنًا بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ )“Luar biasa, betapa beratnya lima perkara dalam timbangan: ‘Lā ilāha illallāh’, ‘Allāhu akbar’, ‘Subhānallāh’, ‘Alhamdulillāh’, dan anak saleh yang meninggal lalu kedua orang tuanya bersabar dan mengharap pahala. Dan beliau juga bersabda: ‘Luar biasa, lima hal siapa yang menemui Allah dengan keyakinan terhadapnya akan masuk surga: beriman kepada Allah, hari akhir, surga, neraka, kebangkitan setelah mati, dan hisab (perhitungan amal).’” (HR. Ahmad no. 15107; disahihkan oleh al-Albani dalam As-Silsilah Ash-Shahīhah)5. Akhlak yang MuliaDari Abu ad-Darda’, Nabi ﷺ bersabda:مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ“Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik.” (HR. Abu Dawud no. 4799; disahihkan oleh al-Albani)Dalam riwayat lain, dari Ummu ad-Darda’, dari suaminya Abu ad-Darda’, ia berkata: “Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ“Tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan shalat malam.” (HR. at-Tirmidzi no. 2003; disahihkan oleh al-Albani) 6. Mengiringi Jenazah hingga Selesai DikebumikanDari Ubay, Nabi ﷺ bersabda:مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِهِ مِنْ أُحُدٍ “Barang siapa mengikuti jenazah hingga dishalatkan dan selesai dimakamkan, maka baginya dua qirath pahala. Dan siapa yang hanya mengikuti hingga dishalatkan, maka baginya satu qirath. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh dua qirath itu lebih berat di timbangan daripada Gunung Uhud.” (HR. Ahmad no. 20256; disahihkan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jāmi‘ ash-Shaghīr) KesimpulanSegala amal saleh, sekecil apa pun, akan mendapatkan balasan dari Allah. Namun, amal-amal tertentu yang disebutkan dalam hadits memiliki keistimewaan luar biasa dalam menambah berat timbangan kebaikan di Hari Kiamat. Karenanya, perbanyaklah dzikir, jaga akhlak, bersabar atas ujian, dan bersegera dalam amal-amal kebaikan.اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَوَازِينَنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ثَقِيلَةً بِالحَسَنَاتِ، وَخَفِيفَةً بِالسَّيِّئَاتِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِآبَائِنَا وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ.“Ya Allah, jadikanlah timbangan amal kami pada Hari Kiamat berat dengan kebaikan, ringan dari dosa, dan ampunilah kami, kedua orang tua kami, serta seluruh kaum muslimin.” Referensi: Islamqa.Com | Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid Ditulis saat hujan turun di Paliyan Gunungkidul, 30 Rabiul Akhir 1447 H, 21 Oktober 2025Penulis: Dr. Muhammad Abduh Tuasikal Artikel Rumaysho.Com Tagsakhlak mulia amal kebaikan amal saleh amalan berat di timbangan Dzikir hari kiamat la ilaha illallah mizan mizan hari kiamat pahala besar sabar atas musibah timbangan timbangan amal timbangan hari kiamat
Daftar Isi
TogglePengertian dan ciri-ciri isim maa la yansharifMakna mamnu‘ min ash-sharfSebab-sebab suatu isim menjadi maa la yansharifI‘rab isim maa la yansharifPengecualian: bisa kasrah jika …Pertama, ketika menjadi mudhafKedua, ketika dimulai dengan al (ال)Kesimpulan singkatKelanjutan dari pembahasan isim yang di-i‘rab dengan tanda cabang pada artikel ini berfokus pada isim kelima, yaitu isim maa la yansharif. Isim ini memiliki keistimewaan karena tidak menerima tanwin dan pada posisi majrur ditandai dengan fathah, bukan kasrah, kecuali dalam keadaan tertentu. Kekhususan tersebut menunjukkan betapa sistem i‘rab dalam bahasa Arab tidak hanya bersandar pada kaidah umum, tetapi juga memiliki variasi khusus yang memperkaya pemahaman gramatikal. Dalam ilmu nahwu, isim–isim (kata benda) secara umum dapat berubah sesuai dengan posisi i’rab-nya, yakni marfu‘ (رفع), manshub (نصب), dan majrur (جر). Namun, terdapat sebagian isim yang tidak mengikuti tanda i‘rab pada umumnya, terutama pada posisi jar. Isim semacam ini disebut dengan “isim maa la yansharif” atau dalam istilah lain disebut juga dengan “mamnu‘ min ash-sharf”.Pengertian dan ciri-ciri isim maa la yansharifIbnu Hisyam menyatakan bahwa, “Isim maa la yansharif ketika berkedudukan majrur (dimasuki huruf jarr), maka tanda i‘rab-nya berupa fathah, bukan kasrah.Contohnya adalah:بِأَفْضَلَ مِنْهُ“Dengan orang yang lebih utama darinya.”Namun, hal tersebut berlaku dengan syarat bahwa isim tersebut tidak dimasuki “al” (ال) dan tidak dalam susunan idhafah.Contoh isim yang dimasuki “al”:بِٱلْأَفْضَلِ“Dengan orang yang paling utama.”Contoh isim yang dalam susunan idhafah:بِأَفْضَلِكُمْ“Dengan orang yang paling utama di antara kalian.”Kedua contoh di atas tetap memakai kasrah pada huruf akhir isim tersebut karena gugurnya status sebagai isim maa la yansharif disebabkan adanya “al” atau karena berupa susunan idhafah.Makna mamnu‘ min ash-sharfSecara harfiah, mamnu‘ min ash-sharf berarti “yang dilarang menerima tanwin”. Karena itu, isim jenis ini tidak boleh di-tanwin, sebab tanwin itu sendiri merupakan sharf. Isim ini disebut maa la yansharif karena diawali oleh kata “laa” (لا), yang menunjukkan penafian. Atau dengan penamaan lain, isim ini diawali oleh kata mamnu’ yang menunjukkan penafian juga.Sebab-sebab suatu isim menjadi maa la yansharifSuatu isim bisa menjadi maa la yansharif jika memenuhi: dua sebab dari sembilan, atau satu sebab tertentu yang cukup kuat untuk menjadi isim maa la yansharif.Beberapa contoh berikut menggambarkan hal tersebut:أَحْمَدُ“Seorang yang bernama Ahmad.”
Kata tersebut termasuk isim maa la yansharif karena memiliki dua sebab, yaitu berstatus sebagai nama orang mengikuti wazn (pola) fi‘il. Contoh lainya adalah:عَطْشَانُ“Laki-laki yang haus.”Isim tersebut tergolong isim maa la yansharif karena ada dua sebab atau alasan, yaitu merupakan sifat dan terdapat alif serta nun di akhir kata.مَسَاجِدُ“Masjid-masjid.”Isim di atas termasuk maa la yansharif karena ada satu sebab yang kuat menjadikan isim tersebut isim maa la yansharif, yaitu dikarenakan isim tersebut berupa shighah muntahaa al-jumu‘, yaitu bentuk jama’ yang paling puncak.I‘rab isim maa la yansharifIsim ini tetap mengikuti kaidah perubahan i‘rab (mu‘rab), namun memiliki tanda khusus pada kedudukan jar (majrur). Tanda-tanda dari masing kedudukan tersebut adalah:Pertama, marfu‘ dengan dhammah (ضمة).Kedua, manshub dengan fathah (فتحة).Ketiga, majrur juga dengan fathah (فتحة), bukan kasrah.Contohnya dalam kalimat adalah:حَضَرَ أَحْمَدُ“Telah hadir seseorang bernama Ahmad.”Kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas merupakan isim maa laa yansharif, marfu’ dengan tanda dhammah sebagai fa’il.رَدَّ ٱللّٰهُ يُوسُفَ إِلَىٰ يَعْقُوبَ“Allah mengembalikan Yusuf kepada Ya‘qub.”Kata يُوسُفَ pada kalimat di atas berkedudukan manshub dengan tanda fathah sebagai maf’ul bih dan kata يَعْقُوب berkedudukan majrur karena didahului oleh huruf jer dan majrur dengan tanda fathah karena kata tersebut merupakan isim maa la yansharif. Pengecualian: bisa kasrah jika …Terdapat dua kondisi di mana isim maa la yansharif boleh berkasrah, meskipun biasanya majrur dengan fathah, yaitu:Pertama, ketika menjadi mudhafContohnya adalah:وَعَظْتُ فِي مَسَاجِدِ ٱلْقَرْيَةِ“Aku memberi nasihat di masjid-masjid kampung itu.”Kata مَسَاجِد pada kalimat di atas berkedudukan majrur dengan tanda kasrah karena didahului oleh huruf jer. Kata tersebut majrur dengan tanda kasrah karena tergolong isim mufrad, bukan lagi isim maa la yansharif. Isim tersebut batal sebagai isim maa la yansharif dikarenakan berkedudukan sebagai mudhaf untuk kata ٱلْقَرْيَة.مَرَرْتُ بِأَفْضَلِكُمْ“Aku melewati orang paling mulia di antara kalian.”Kata أَفْضَلِ pada kalimat d iatas berkedudukan majrur dengan tanda kasrah karena didahului oleh huruf jer. Kata tersebut majrur dengan tanda kasrah karena tergolong isim mufrad, bukan lagi isim maa la yansharif. Isim tersebut batal sebagai isim maa la yansharif dikarenakan berkedudukan sebagai mudhaf untuk kata setelahnya yang berupa dhamir.Kedua, ketika dimulai dengan al (ال)Contohnya dalam kalimat adalah:سَأَلْتُ عَنِ ٱلْأَفْضَلِ مِنَ ٱلطُّلَّابِ“Aku bertanya tentang murid yang paling pintar.”Kata ٱلْأَفْضَلِ pada kalimat di atas berkedudukan majrur dengan tanda kasrah karena didahului oleh “al”, sehingga tidak lagi berstatus maa la yansharif secara hukum.Kesimpulan singkatIsim maa la yansharif adalah isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menggunakan kasrah saat majrur, melainkan fathah. Hal ini disebabkan oleh satu atau dua sebab tertentu, seperti pola kata, sifat, atau bentuk jamak tertentu. Namun, aturan ini gugur apabila isim tersebut menjadi mudhaf atau dimasuki al (ال). Dalam dua kondisi itu, ia kembali mengikuti i‘rab seperti biasa, yaitu dengan kasrah saat majrur.[Bersambung]Kembali ke bagian 24 Lanjut ke bagian 26***Penulis: Rafi NugrahaArtikel Muslim.or.id
Hari Kiamat adalah peristiwa agung yang pasti terjadi dan menjadi puncak dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Pada hari itu, seluruh amal perbuatan akan ditampakkan, hisab ditegakkan, dan setiap jiwa menerima balasan yang adil dari Allah Ta‘ala. Para ulama menjelaskan bahwa kejadian-kejadian besar di Hari Kiamat berlangsung dalam urutan yang sangat teratur, dimulai dari kebangkitan manusia hingga berakhir di surga atau neraka. Tulisan ini menguraikan secara lengkap tahapan-tahapan Hari Kiamat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Syarh Ath-Thahawiyyah. Yang telah disepakati oleh para ulama yang teliti adalah bahwa urutan peristiwa pada Hari Kiamat berlangsung sebagai berikut:Ketika manusia dibangkitkan dan bangun dari kubur mereka, mereka akan menuju ke Padang Mahsyar. Di sana mereka berdiri sangat lama; keadaan mereka menjadi amat berat dan dahaga pun sangat mencekik. Ketakutan luar biasa meliputi mereka karena lamanya waktu berdiri itu, serta keyakinan mereka bahwa perhitungan amal akan segera dimulai, dan karena apa yang akan Allah `ʿazza wa jalla` lakukan terhadap mereka.Ketika masa berdiri itu sudah berlangsung lama, Allah `ʿazza wa jalla` akan menampakkan terlebih dahulu telaga Nabi-Nya ﷺ, yaitu Haudh al-Maurūd. Telaga Nabi ﷺ itu berada di tengah padang Mahsyar, ketika manusia sedang berdiri lama menanti keputusan Rabb semesta alam, pada hari yang kadarnya seperti lima puluh ribu tahun lamanya. Maka, siapa pun yang meninggal dunia di atas sunnah beliau — tanpa mengubah, tanpa membuat bid‘ah, dan tanpa mengganti ajaran — akan mendatangi telaga itu dan minum darinya. Dengan demikian, tanda pertama keselamatan baginya adalah bahwa ia diberi minum dari telaga Nabi ﷺ. Setelah itu, setiap nabi akan ditampakkan pula telaganya masing-masing, dan orang-orang saleh dari umat mereka akan diberi minum dari telaga tersebut.Kemudian manusia berdiri kembali dalam waktu yang sangat lama, hingga tibalah syafaat kubra (syafaat agung, syafaatul ‘uzhma), yaitu syafaat Nabi ﷺ, agar Allah `ʿazza wa jalla` mempercepat dimulainya hisab seluruh makhluk. Dalam hadits panjang yang masyhur disebutkan bahwa manusia mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim, dan seterusnya, hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad ﷺ. Mereka berkata kepadanya, “Wahai Muhammad,” sambil menjelaskan keadaan mereka yang sangat berat, dan mereka memintanya untuk memohon kepada Allah agar segera memulai hisab sehingga manusia terhindar dari kesulitan yang panjang itu. Maka Rasulullah ﷺ bersabda setelah mendengar permintaan mereka, “Aku-lah orangnya, aku-lah orangnya (yang mampu melakukannya).”* Beliau kemudian datang ke hadapan ‘Arsy, lalu sujud dan memuji Allah `ʿazza wa jalla` dengan pujian-pujian yang Allah bukakan bagi beliau. Setelah itu, dikatakan kepadanya: “Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah niscaya engkau akan diberi, dan berilah syafaat niscaya syafaatmu akan diterima.” Maka inilah syafaat agung Nabi ﷺ, yaitu syafaat beliau agar Allah mempercepat hisab bagi seluruh makhluk.Setelah itu, tibalah tahap al-‘arḍ (عرض الأعمال) — yakni penampakan amal-amal perbuatan.Kemudian setelah penampakan amal tersebut, terjadilah hisab (perhitungan amal).Setelah hisab pertama, catatan-catatan amal akan beterbangan. Adapun hisab pertama ini termasuk dalam bagian dari penampakan amal, karena di dalamnya terjadi perdebatan dan alasan-alasan pembelaan diri dari para manusia.Setelah itu, catatan-catatan amal tersebut diterbangkan, lalu orang-orang yang beriman (Ahlul Yamin) menerima kitab mereka dengan tangan kanan, sedangkan orang-orang kafir dan durhaka (Ahlus Syimal) menerimanya dengan tangan kiri mereka. Maka tibalah saat mereka membaca kitab catatan amal masing-masing.Kemudian setelah pembacaan kitab amal itu, terjadi lagi perhitungan, untuk memutus segala alasan dan menegakkan hujjah (bukti) atas manusia melalui pembacaan apa yang tertulis dalam kitab amal mereka.Setelah itu datanglah tahap mīzān (timbangan), di mana amal-amal perbuatan manusia akan ditimbang — sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.Kemudian setelah proses penimbangan itu, manusia akan terbagi menjadi kelompok-kelompok dan golongan-golongan (azwāj), yaitu setiap jenis akan dikumpulkan bersama dengan yang sejenis. Pada saat itu akan ditegakkan panji-panji para nabi — Liwa’ Muhammad ﷺ, Liwa’ Ibrahim, Liwa’ Musa, dan lainnya. Manusia akan bernaung di bawah panji-panji tersebut sesuai dengan jenis dan kedudukan mereka. Setiap kelompok akan dikumpulkan dengan kelompoknya yang serupa. Demikian pula orang-orang zalim dan kafir, mereka juga akan dihimpun bersama dengan yang serupa, sebagaimana firman Allah Ta‘ala: “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman-teman mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah.” (QS. As-Saffat: 22–23). Maksudnya dengan azwājahum (pasangan-pasangan mereka) adalah orang-orang yang sejenis dan serupa dengan mereka, baik dalam keyakinan maupun perbuatan. Maka ulama-ulama kaum musyrik akan dihimpun bersama ulama musyrik lainnya, para penguasa zalim akan dihimpun bersama para zalim lainnya, orang-orang yang mengingkari kebangkitan akan dihimpun bersama sesama pengingkar kebangkitan, dan demikian seterusnya.Setelah itu, Allah ‘Azza wa Jalla menebarkan kegelapan sebelum Jahanam (neraka) — kita berlindung kepada Allah darinya — dan manusia akan berjalan dengan cahaya (nūr) yang diberikan kepada mereka. Umat ini (umat Muhammad ﷺ) akan berjalan di antara mereka terdapat kaum munafik. Ketika mereka berjalan dengan cahaya masing-masing, maka didirikanlah tembok pemisah (as-sūr) yang telah Allah sebutkan, “Lalu dipasanglah dinding di antara mereka yang mempunyai pintu; di sebelah dalamnya ada rahmat, sedangkan di sebelah luarnya dari arah mereka ada azab. Mereka (orang-orang munafik) memanggil orang-orang beriman: ‘Bukankah kami dahulu bersama kalian?’ Mereka menjawab: ‘Benar, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri…’” (QS. Al-Hadid: 13–14). Maka Allah memberikan cahaya kepada orang-orang beriman, sehingga mereka dapat melihat dan menapaki jalan menuju Ash-Shirāṭ (titian di atas neraka). Adapun orang-orang munafik tidak diberi cahaya, dan mereka akhirnya bersama orang-orang kafir, terjatuh dan terhempas ke dalam neraka, berjalan dalam kegelapan, sedangkan di depan mereka terbentang Jahanam — na‘ūdzu billāh.Setelah itu, Nabi ﷺ datang pertama kali dan berdiri di atas Shirāṭ, beliau berdoa kepada Allah ‘Azza wa Jalla untuk dirinya dan untuk umatnya seraya berkata: “Allāhumma sallim, sallim. Allāhumma sallim, sallim.” (“Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah!”). Maka beliau ﷺ pun meniti Shirāṭ, dan umatnya pun meniti Shirāṭ. Setiap orang akan melaluinya sesuai dengan kadar amalnya, dan cahaya yang menyertai mereka juga sesuai kadar amalnya. Maka berjalanlah mereka yang telah diampuni oleh Allah ‘Azza wa Jalla, sedangkan sebagian lain terjatuh ke dalam neraka, di lapisan para ahli tauhid yang Allah kehendaki untuk disiksa terlebih dahulu. Setelah mereka selesai melewati neraka, mereka berkumpul di lapangan surga (ʿarashāt al-jannah) — yakni di tempat yang telah Allah siapkan bagi orang-orang beriman untuk saling menuntut keadilan di antara mereka, agar setiap hak dikembalikan kepada pemiliknya. Lalu Allah menghapus segala rasa dengki dan dendam dari hati mereka, sehingga mereka memasuki surga dalam keadaan hati yang bersih, tanpa kebencian sedikit pun.Kemudian yang pertama kali memasuki surga setelah Nabi ﷺ adalah para fakir dari kalangan Muhajirin, disusul para fakir dari kalangan Anshar, lalu para fakir dari umat beliau secara umum. Adapun orang-orang kaya akan tertunda masuk surga, karena mereka harus menyelesaikan perhitungan terkait tanggung jawab terhadap sesama makhluk, serta pertanggungjawaban atas harta mereka di hadapan Allah.(Sumber: “Syarh Ath-Thahawiyyah”, hlm. 542, dengan penomoran Maktabah Syamilah, karya Syaikh Shalih Alu Syaikh, dengan sedikit penyesuaian redaksi)Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat di hari yang penuh dahsyat itu, diberi cahaya untuk meniti shirath, dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad ﷺ di surga-Nya yang abadi. Aamiin. Referensi: Islamqa.Com | Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid Ditulis saat hujan turun di Wonosari Gunungkidul, 30 Rabiul Akhir 1447 H, 21 Oktober 2025Penulis: Dr. Muhammad Abduh Tuasikal Artikel Rumaysho.Com Tagscatatan amal hari kiamat hisab keadilan Allah kebangkitan manusia mizan mizan hari kiamat shirath surga dan neraka syafaat nabi timbangan timbangan amal timbangan hari kiamat urutan hari kiamat
مَفاتيحُ الرِّزق الحَلال
Oleh:
Dr. Mahmud bin Ahmad ad-Dosari
د. محمود بن أحمد الدوسري
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:
مِنْ أَكْثَرِ الْهُمُومِ الَّتِي تَشْغَلُ النَّاسَ وَتُرْهِقُهُمْ؛ هَمُّ تَحْصِيلِ الرِّزْقِ، مَعَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ رِزْقَهُ بَيْنَ الْخَلَائِقِ، وَضَمِنَ لَهُمْ ذَلِكَ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذَّارِيَاتِ: 56-58]
Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Rasul-Nya yang mulia, dan kepada para keluarga dan seluruh sahabat beliau. Amma ba’du:
Di antara beban pikiran yang banyak menyibukkan dan meletihkan manusia adalah beban pikiran dalam mencari rezeki. Padahal, Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengatur pembagian rezeki-Nya di antara seluruh makhluk-Nya dan menjamin itu bagi mereka melalui firman-Nya Ta’ala:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku. Sesungguhnya Allahlah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” (QS. Adz-Dzariyat: 56-58).
وَمَفَاتِيحُ الرِّزْقِ الْحَلَالِ كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَارِكَ اللَّهُ لَهُ فِي رِزْقِهِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ هَذِهِ الْأُمُورَ الْمُهِمَّةَ:
1- التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، مَعَ الْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ: تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا» صَحِيحٌ – رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِالسَّعْيِ فِي الْأَرْضِ لِتَحْصِيلِ الْمَعَاشِ: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ [الْمُلْكِ: 15]؛ وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الْجُمُعَةِ: 10].
Kunci-kunci rezeki halal ada banyak dan beraneka ragam, siapa yang ingin Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberkahi rezekinya, maka hendaklah dia memperhatikan hal-hal penting berikut ini:
Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan diiringi dengan ikhtiar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:
لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ: تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا
“Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan sebenar-benarnya takwa, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti halnya burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang.” (Hadis sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi).
Namun, selain bertawakal, Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga memerintahkan kita untuk melakukan usaha di muka bumi agar dapat memperoleh penghidupan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15). Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman:
فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“Apabila salat (Jum’at) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10).
2- تَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتُهُ، وَالْبُعْدُ عَنِ الْمَعَاصِي: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطَّلَاقِ: 2-3]؛ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الْأَعْرَافِ: 96].
Bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan menjauhi kemaksiatan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
“Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga.” (QS. At-Talaq: 2-3). Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi” (QS. Al-A’raf: 96).
3- الْبُعْدُ عَنِ الْحَرَامِ، وَتَحْصِيلُ الرِّزْقِ الْحَلَالِ: عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنِ الْحَرَامِ، وَيَجْتَهِدَ فِي تَحْصِيلِ الْكَسْبِ الْحَلَالِ؛ حَتَّى يُوَسِّعَ اللَّهُ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [الْمُؤْمِنُونَ: 51]؛ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [الْبَقَرَةِ: 172]، وَقَدْ أَوْدَعَ اللَّهُ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ مُؤَشِّرًا يَدُلُّهُ عَلَى الْخَيْرِ، أَوْ يَصْرِفُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: «الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
Menjauhi perkara haram dan mengusahakan rezeki yang halal
Setiap Muslim harus menjauhi hal yang haram dan berusaha mencari pendapatan yang halal, agar Allah Subhanahu Wa Ta’ala melapangkan rezeki baginya dan memberkahinya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
“Allah berfirman, ‘Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramal salihlah, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan!” (QS. Al-Mu’minun: 51). Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu” (QS. Al-Baqarah: 172).
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menanamkan dalam hati setiap Muslim, alarm yang mengarahkannya kepada kebaikan atau mengalihkannya dari keburukan, diriwayatkan dari An-Nawwas bin Sam’an Al-Anshari Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam tentang kebaikan dan dosa. Lalu beliau bersabda:
الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
‘Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah hal yang mengusik hatimu dan kamu tidak suka jika itu diketahui orang lain.” (HR. Muslim).
4- التَّوْبَةُ وَكَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ: فَإِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشُّورَى: 30]، وَالِاسْتِغْفَارُ يَرْفَعُ الْبَلَاءَ، وَيُزِيلُ النِّقَمَ، وَيَفْتَحُ أَبْوَابَ الرِّزْقِ وَالنَّمَاءِ؛ قَالَ تَعَالَى – عَلَى لِسَانِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [نُوحٍ: 10-12].
Bertobat dan banyak beristighfar
Seorang hamba akan terhalang dari rezekinya akibat dosa yang dia perbuat. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
“Musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan (Allah) memaafkan banyak (kesalahanmu).” (QS. Asy-Syura: 30).
Sedangkan istighfar akan mengangkat bala, menghilangkan musibah, dan membuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman – melalui lisan Nabi Nuh Alaihissalam:
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
“Maka aku berkata (kepada mereka), ‘Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.’” (QS. Nuh: 10-12).
5- شُكْرُ النِّعَمِ: بِالشُّكْرِ تَزْدَادُ النِّعَمُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إِبْرَاهِيمَ: 7]، وَبِالشُّكْرِ أَمَرَ الْأَنْبِيَاءُ أَقْوَامَهُمْ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ: ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الْعَنْكَبُوتِ: 17]؛ وَهُوَ وَصِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ كَمَا قَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: “اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ”» صَحِيحٌ – رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
Mensyukuri nikmat
Dengan rasa syukur, kenikmatan akan bertambah, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
“(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.’” (QS. Ibrahim: 7).
Para Nabi juga memerintahkan kaum mereka untuk senantiasa bersyukur, Nabi Ibrahim Alaihissalam berkata kepada kaumnya:
فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
“Maka mintalah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.” (QS. Al-Ankabut: 17).
Ini juga menjadi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam kepada para sahabat, beliau bersabda:
أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: “اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
“Wahai Muadz! Janganlah kamu sekali-kali meninggalkan doa di setiap akhir shalat: ‘Ya Allah berilah pertolongan kepadaku untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepada-Mu.’” (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i).
6- صِلَةُ الرَّحِمِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَمَنْ يَقْطَعْ رَحِمَهُ؛ يَقْطَعِ اللَّهُ عَنْهُ الْخَيْرَ؛ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ؛ قَالَتِ الرَّحِمُ: “هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ”. قَالَ: نَعَمْ؛ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، قَالَتْ: “بَلَى يَا رَبِّ”. قَالَ: فَهْوَ لَكِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
Bersilaturahmi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
“Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi.” (HR. Al-Bukhari).
Siapa yang memutus silaturahminya, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan memutus kebaikan darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:
إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ؛ قَالَتِ الرَّحِمُ: “هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ”. قَالَ: نَعَمْ؛ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، قَالَتْ: “بَلَى يَا رَبِّ”. قَالَ: فَهْوَ لَكِ
“Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk, setelah selesai menciptakannya, rahim berkata, ‘Inilah saatnya untuk berlindung kepada Engkau dari pemutusan hubungan!’ Allah lalu berfirman, ‘Ya, apakah kamu suka jika Aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu dan Aku memutus hubungan dengan orang yang memutusmu?’ Rahim berkata, ‘Tentu, wahai Tuhanku!’ Allah berfirman, ‘Kalau begitu itulah (yang akan Aku lakukan) bagimu.’” (HR. Al-Bukhari).
7- الْإِنْفَاقُ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سَبَأٍ: 39]، وَفِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْفِقْ؛ أُنْفِقْ عَلَيْكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ أَيْضًا: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ؛ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
Berinfak di berbagai jalan kebaikan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
“Apapun yang kamu infakkan pasti Dia (Allah) akan menggantinya.” (QS. Saba: 39).
Dalam hadis qudsi disebutkan:
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْفِقْ؛ أُنْفِقْ عَلَيْكَ
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, “Wahai manusia! Berinfaklah, niscaya Aku akan berinfak kepadamu.” (HR. Muslim).
Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ
“Sedekah tidak akan mengurangi sedikit pun harta.” (HR. Muslim).
Beliau juga bersabda:
مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ؛ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا
“Tidaklah ada seorang hamba yang memasuki pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun, lalu salah satunya berkata, ‘Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang memberi!’ sedangkan malaikat lainnya berkata, ‘Ya Allah, berilah kerusakan (harta) bagi orang yang pelit!’” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
8- التَّفَرُّغُ لِلْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ: وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنْ يَنْقَطِعَ الْمُسْلِمُ عَنِ التَّكَسُّبِ وَالْعَمَلِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: أَنْ يَتَوَقَّفَ عَنِ الْعَمَلِ لِيُؤَدِّيَ الْفَرَائِضَ وَالْعِبَادَاتِ؛ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الْجُمُعَةِ: 9]، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي؛ أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ؛ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ» صَحِيحٌ – رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
Fokus menjalankan ibadah dan ketaatan
Maksudnya bukan berhenti dari bekerja dan berusaha, tetapi menghentikan pekerjaan saat harus menunaikan kewajiban dan ibadah, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jum’at telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah: 9).
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي؛ أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ؛ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ
“Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, ‘Wahai manusia, fokuslah beribadah kepada-Ku! Niscaya Aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan menutup kemiskinanmu. Dan jika itu tidak kamu lakukan, maka Aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutup kemiskinanmu.” (Hadis sahih – riwayat At-Tirmidzi).
الخطبة الثانية
الْحَمْدُ لِلَّهِ… أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ.. وَمِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، وَتُبَارِكُ فِيهِ:
9- الْإِحْسَانُ إِلَى الضُّعَفَاءِ وَالْمُحْتَاجِينَ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ: أَنَّ عِبَادَةَ الضُّعَفَاءِ وَدُعَاءَهُمْ أَشَدُّ إِخْلَاصًا وَأَكْثَرُ خُشُوعًا؛ لِخَلَاءِ قُلُوبِهِمْ مِنَ التَّعَلُّقِ بِزُخْرُفِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا، وَصَفَاءِ ضَمَائِرِهِمْ مِمَّا يَقْطَعُهُمْ عَنِ اللَّهِ، فَجَعَلُوا هَمَّهُمْ وَاحِدًا؛ فَزَكَتْ أَعْمَالُهُمْ).
Khutbah Kedua
Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Wahai kaum Muslimin! Di antara hal lainnya yang dapat menambah rezeki dan mendatangkan keberkahannya adalah:
Berbuat baik kepada orang-orang lemah dan membutuhkan
Diriwayatkan dari Mushab bin Saad bin Abi Waqqash, ia mengatakan, “Saad bin Abi Waqqash Radhiyallahu ‘anhu (yakni ayahnya sendiri) pernah merasa punya kelebihan daripada orang yang lebih rendah darinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda kepadanya:
هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ
‘Bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian?!’” (HR. Al-Bukhari).
Ibnu Baththal Rahimahullah berkata, “Makna dari hadis ini bahwa ibadah dan doa orang-orang lemah lebih ikhlas dan khusyuk, karena hati mereka dapat terlepas dari keterkaitan dengan kenikmatan dan perhiasan dunia, dan kebersihan hati mereka dari hal-hal yang dapat memutus mereka dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka dari itu, mereka menjadikan tujuan mereka hanya satu (yakni akhirat), sehingga amalan-amalan mereka bersih.”
10- الْمُتَابَعَةُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» صَحِيحٌ – رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
Menyambung haji dengan umrah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:
تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
“Sambunglah antara haji dengan umrah, karena keduanya dapat menyingkirkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana perapian dapat menyingkirkan karat-karat besi, emas, dan perak.” (Hadis sahih – diriwayatkan oleh At-Tirmidzi).
11- الزَّوَاجُ: مِنَ الْمَفَاهِيمِ الْخَاطِئَةِ تَرْكُ الزَّوَاجِ؛ بِحُجَّةِ عَدَمِ تَوَفُّرِ الْإِمْكَانَاتِ الْمَادِّيَّةِ! وَاللَّهُ تَعَالَى يَرُدُّ عَلَى هَذَا الْفَهْمِ الْخَاطِئِ وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النُّورِ: 32]؛ وَالْمَعْنَى: لَا يَمْنَعْكُمْ مَا تَتَوَهَّمُونَ: مِنْ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ؛ افْتَقَرَ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْعَائِلَةِ وَنَحْوِهِ! وَفِيهِ حَثٌّ عَلَى التَّزَوُّجِ، وَوَعْدٌ لِلْمُتَزَوِّجِ بِالْغِنَى بَعْدَ الْفَقْرِ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: بَابُ: تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النُّورِ: 32]، ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ الْبَابِ؛ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا فَقِيرًا بِمَا يَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ؛ فَقَالَ لَهُ: «مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
Menikah
Suatu pemahaman yang salah jika seseorang menghindari pernikahan dengan alasan tidak memiliki kemampuan finansial. Padahal, Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah membantah pemahaman keliru ini melalui firman-Nya:
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).
Yakni jangan sampai menghalangi kalian dari pernikahan apa yang kalian sangkakan itu bahwa jika seseorang menikah maka ia akan miskin akibat banyaknya tanggungan nafkah dan lain sebagainya! Ayat ini juga mengandung anjuran untuk menikah dan janji bagi orang yang menikah akan memberinya kecukupan setelah kekurangan.
Imam Al-Bukhari Rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, “Bab menikahkan orang yang punya kesulitan ekonomi, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala, ‘Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.’ (QS. An-Nur: 32).”
Kemudian beliau menyebutkan hadis dalam tema ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam menikahkan seorang lelaki miskin dengan mahar hafalan Al-Qur’annya. Beliau bersabda kepada lelaki itu, “Aku menikahkanmu dengan hafalan Al-Qur’an yang kamu miliki.” (HR. Al-Qur’an).
12- إِنْجَابُ الذُّرِّيَّةِ، وَعَدَمُ الْخَوْفِ مِنَ الْفَقْرِ بِسَبَبِهِمْ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ [الْإِسْرَاءِ: 31]. قَالَ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَهَذَا مِنْ رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ؛ حَيْثُ كَانَ أَرْحَمَ بِهِمْ مِنْ وَالِدِيهِمْ، فَنَهَى الْوَالِدِينَ أَنْ يَقْتُلُوا أَوْلَادَهُمْ؛ خَوْفًا مِنَ الْفَقْرِ وَالْإِمْلَاقِ، وَتَكَفَّلَ بِرِزْقِ الْجَمِيعِ).
Melahirkan keturunan dan tidak takut miskin karena kehadiran mereka
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra: 31).
As-Sa’di mengatakan, “Ini merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala bagi para hamba-Nya, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta’ala lebih penyayang kepada anak-anak itu daripada orang tua mereka, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta’ala melarang kedua orang tua membunuh anak-anak mereka karena takut miskin dan kekurangan, dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjamin rezeki mereka semuanya.”
13- الرِّضَا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْقَنَاعَةُ بِمَا أَعْطَانَا اللَّهُ مِنْ نِعَمٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهَ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ» صَحِيحٌ – رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ؛ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا» حَسَنٌ – رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
Ridha dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala berikan
Juga qana’ah (merasa cukup) dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Ta’ala berikan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam telah bersabda:
لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ
“Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kaya jiwa (hati yang merasa cukup).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Beliau Shallallahu Alaihi Wa Sallam juga bersabda:
مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهَ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ
“Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya ada di hatinya, memudahkan urusannya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjadikan kemiskinan ada di depan matanya, mempersulit urusannya, dan tidak akan didatangi dunia kecuali yang telah ditakdirkan untuknya.” (Hadis sahih – riwayat At-Tirmidzi).
Beliau Shallallahu Alaihi Wa Sallam juga bersabda:
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ؛ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا
“Siapa dari kalian yang memasuki waktu pagi dalam keadaan aman di rumahnya, sehat badannya, dan punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan segala kenikmatan dunia telah dikumpulkan baginya.” (Hadis hasan – riwayat At-Tirmidzi).
Sumber:
https://www.alukah.net/web/m.aldosary/0/169120/مفاتيح-الرزق-الحلال/
Sumber artikel PDF
🔍 Cara Menghadiahkan Al Fatihah, Istri Yang Sabar, Pertanyaan Tauhid, Haid Sebulan 2x
Visited 248 times, 3 visit(s) today
Post Views: 342
<img class="aligncenter wp-image-43307" src="https://i0.wp.com/konsultasisyariah.com/wp-content/uploads/2023/10/qris-donasi-yufid-resized.jpeg" alt="QRIS donasi Yufid" width="741" height="1024" />
Menikah adalah ibadah agung yang diatur dengan sangat rinci dalam syariat Islam. Di balik keindahan pernikahan, ada batas-batas yang ditetapkan agar kehormatan dan silaturahim tetap terjaga. Karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mengetahui siapa saja wanita yang haram dinikahi agar tidak terjerumus dalam dosa besar tanpa sadar. Imam Al-Qadhi Abu Syuja’ rahimahullah berkata dalam Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib,فَصْلٌ وَالْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّصِّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ: سَبْعٌ بِالنَّسَبِ، وَهُنَّ: ٱلْأُمُّ وَإِنْ عَلَتْ، وَٱلْبِنْتُ وَإِنْ سَفَلَتْ، وَٱلْأُخْتُ، وَٱلْخَالَةُ، وَٱلْعَمَّةُ، وَبِنْتُ ٱلْأَخِ، وَبِنْتُ ٱلْأُخْتِ. وَٱثْنَتَانِ بِٱلرَّضَاعِ: ٱلْأُمُّ ٱلْمُرْضِعَةُ، وَٱلْأُخْتُ مِنَ ٱلرَّضَاعِ. وَأَرْبَعٌ بِٱلْمُصَاهَرَةِ: أُمُّ ٱلزَّوْجَةِ، وَٱلرَّبِيبَةُ إِذَا دَخَلَ بِٱلْأُمِّ، وَزَوْجَةُ ٱلْأَبِ، وَزَوْجَةُ ٱلِابْنِ. وَوَاحِدَةٌ مِنْ جِهَةِ ٱلْجَمْعِ، وَهِيَ أُخْتُ ٱلزَّوْجَةِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. وَيَحْرُمُ مِنَ ٱلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ ٱلنَّسَبِ.Wanita yang haram dinikahi berdasarkan nash (teks syariat) ada empat belas. Mereka terbagi dalam beberapa sebab:A. Karena hubungan nasab (keturunan), ada tujuh:Ibu, nenek, dan seterusnya ke atas.Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah.Saudara perempuan.Bibi dari pihak ibu (khālah).Bibi dari pihak ayah (‘ammah).Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan dari pihak saudara laki-laki).Anak perempuan saudara perempuan (keponakan dari pihak saudara perempuan).B. Karena hubungan persusuan, ada dua:Ibu susuan.Saudara perempuan sepersusuan.C. Karena hubungan pernikahan (mushāharah), ada empat:Ibu mertua.Anak tiri (jika ibunya sudah digauli).Istri ayah (ibu tiri).Istri anak (menantu perempuan). D. Karena sebab penggabungan dalam satu pernikahan, ada satu:Saudara perempuan istri.Selain itu, tidak boleh pula menggabungkan dalam satu ikatan pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya (baik dari pihak ayah maupun ibu).Kaidahnya, “Segala yang haram karena hubungan nasab, maka haram pula karena persusuan.” PENJELASANMahram Karena Persusuan(Dan dua wanita yang haram dinikahi karena sebab radha‘ (susuan), yaitu ibu susuan dan saudari susuan).Inilah sebab kedua munculnya mahram, yaitu persusuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta‘ala:﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾“Ibu-ibu susuanmu dan saudari-saudari susuanmu.” (QS. An-Nisā’: 23)Ketahuilah bahwa semua yang haram dinikahi karena hubungan nasab (keturunan), juga haram dinikahi karena hubungan persusuan. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi:ايَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِب“Haram karena persusuan apa yang haram karena nasab.”Dua golongan yang haram karena persusuan adalah ibu yang menyusui dan saudara perempuan karena persusuan.
Ini merupakan sebab kedua yang menjadikan seseorang mahram, yaitu radha‘ah (persusuan). Allah Ta‘ālā berfirman:﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾“Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu serta saudara-saudara perempuanmu sepersusuan.” (QS. An-Nisā’: 23)Ketahuilah, segala sesuatu yang haram karena nasab, maka haram pula karena persusuan. Sebagaimana sabda Nabiﷺ:
«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»“Haram karena persusuan itu sama dengan yang haram karena nasab.”Dalam riwayat lain:«مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ» (apa yang haram karena kelahiran). Mahram Hubungan Pernikahan (Musāharah)Empat orang yang haram dinikahi karena musāharah adalah:1. Ibu mertua. Begitu akad nikah sah, ibunya istri dan nenek-neneknya langsung haram untuk dinikahi, baik karena nasab maupun persusuan. Firman Allah:﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾“Dan ibu-ibu dari istri kalian.” (QS. An-Nisā’: 23)Sebagian ulama ada yang berpendapat baru haram jika sudah terjadi hubungan badan, tetapi pendapat ini lemah.2. Anak tiri (rabībah). Yaitu anak dari istri, baik anak kandung maupun anak susuan. Mereka haram dinikahi dengan syarat telah terjadi hubungan badan dengan sang ibu. Jika istri sudah diceraikan sebelum digauli, maka anak tirinya boleh dinikahi. Allah Ta‘ālā berfirman:﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾“Dan (diharamkan atas kalian menikahi) anak-anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kalian campuri. Tetapi jika kalian belum mencampuri mereka, maka tidak berdosa (menikahinya).” (QS. An-Nisā’: 23)3. Istri dari ayah. Termasuk juga istri kakek, baik dari jalur ayah maupun ibu, dan berlaku pula pada nasab maupun persusuan. Firman Allah:﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾“Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayahmu.” (QS. An-Nisā’: 22)4. Istri dari anak (menantu). Termasuk istri cucu dari jalur laki-laki, baik dalam nasab maupun persusuan. Firman Allah:﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾“Dan (diharamkan atas kalian menikahi) istri-istri anak kandung kalian.” (QS. An-Nisā’: 23) Menghimpun dua wanita dalam satu ikatan pernikahanSalah satu bentuk keharaman nikah adalah menghimpun dua wanita sekaligus, yaitu menikahi seorang wanita bersama saudari perempuannya. Tidak boleh bagi seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan saudarinya, baik mereka saudari kandung seayah-seibu, seayah saja, atau seibu saja. Sama saja apakah saudari itu karena nasab ataupun karena persusuan.Dalilnya adalah firman Allah Ta‘ālā:﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾
“Dan diharamkan atas kamu menghimpun (dalam pernikahan) dua orang saudari, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.” (QS. An-Nisā’: 23)Dalam hadits juga disebutkan:
«مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ الْأُخْتَيْنِ»
“Terlaknat orang yang menyatukan maninya dalam rahim dua orang saudari.”Demikian pula, haram menghimpun seorang wanita dengan bibinya dari jalur ayah (bibi kandung) maupun bibinya dari jalur ibu. Nabi ﷺ bersabda:«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»
“Tidak boleh menghimpun seorang wanita dengan bibinya dari jalur ayah, dan tidak pula dengan bibinya dari jalur ibu.”Alasan larangan ini adalah karena pernikahan seperti itu bisa menimbulkan permusuhan dan menyebabkan terputusnya silaturahim. Maka sebagaimana haram menghimpun wanita dengan bibinya, haram pula menghimpun wanita dengan anak perempuan saudaranya (keponakan), baik dari pihak saudara laki-laki maupun saudara perempuan, serta anak-anak mereka (cucu keponakan). Sama saja, baik karena nasab maupun karena persusuan.Kaidah umum (ḍābiṭ) dari siapa saja yang haram dihimpun dalam satu pernikahan adalah: dua perempuan yang apabila salah satunya dianggap sebagai laki-laki, maka ia tidak halal menikahi yang lainnya karena hubungan kekerabatan. Referensi: Kifayah Al-Akhyar @ Pondok Darush Sholihin Gunungkidul, 29 Rabiul Akhir 1447 H, 21 Oktober 2025Dr. Muhammad Abduh TuasikalArtikel Rumaysho.Com Tagsfikih nikah hukum nikah hukum pernikahan islam larangan menikah mahram matan taqrib matan taqrib kitab nikah musaharah nasab nikah siapakah mahram susuan wanita haram dinikahi

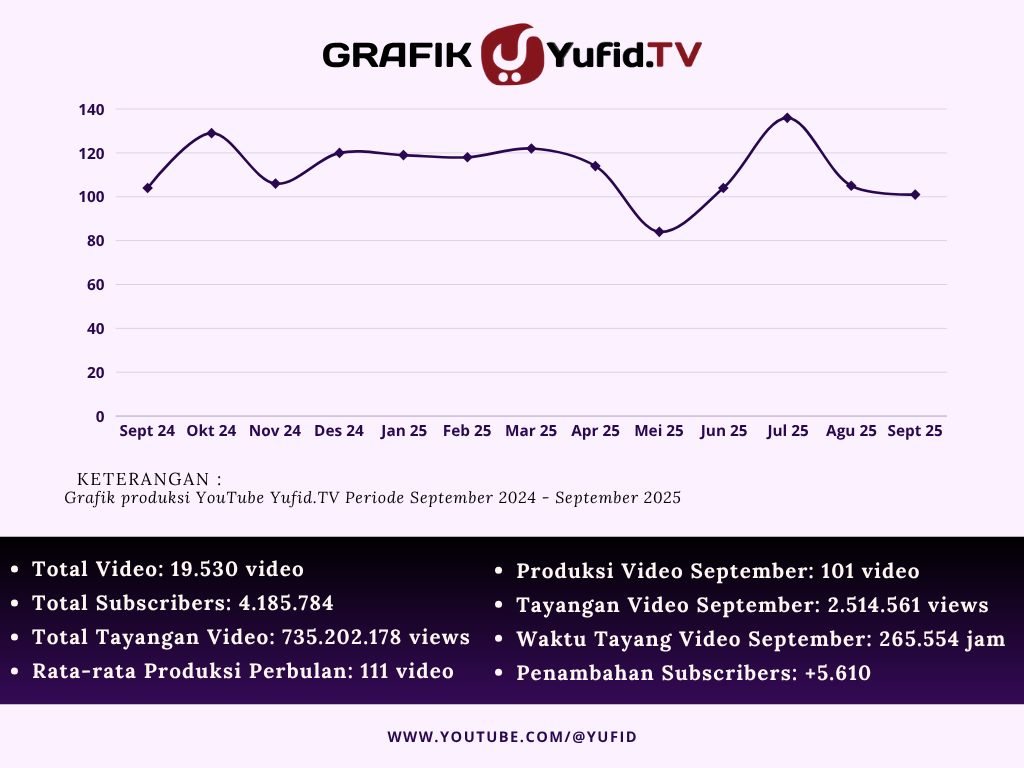 Total Video Yufid.TV: 19.530 video
Total Subscribers: 4.185.784 subscribers
Total Tayangan Video: 735.202.178 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 111 video
Produksi Video September 2025: 101 video
Tayangan Video September 2025: 2.514.561 views
Waktu Tayang Video September 2025: 265.554 jam
Penambahan Subscribers September 2025: +5.610
Selama bulan September 2025 tim Yufid menyiarkan 129 video live.
Channel YouTube YUFID EDU
Total Video Yufid.TV: 19.530 video
Total Subscribers: 4.185.784 subscribers
Total Tayangan Video: 735.202.178 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 111 video
Produksi Video September 2025: 101 video
Tayangan Video September 2025: 2.514.561 views
Waktu Tayang Video September 2025: 265.554 jam
Penambahan Subscribers September 2025: +5.610
Selama bulan September 2025 tim Yufid menyiarkan 129 video live.
Channel YouTube YUFID EDU
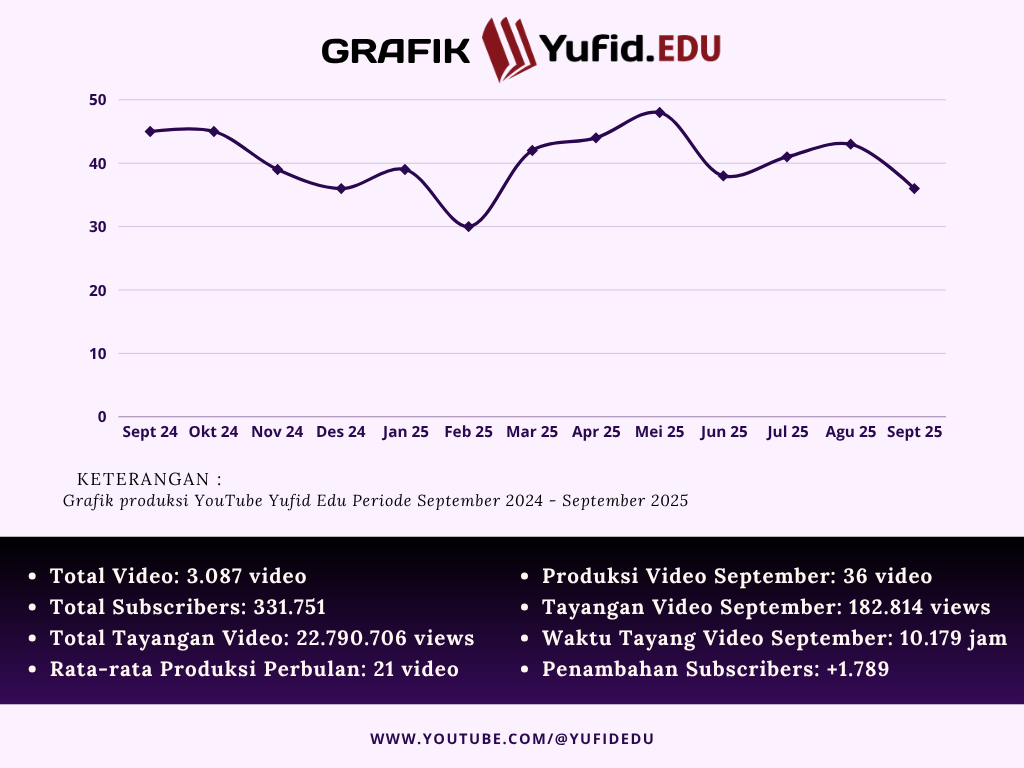 Total Video Yufid Edu: 3.087 video
Total Subscribers: 331.751
Total Tayangan Video: 22.790.706 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 21 video
Produksi Video September 2025: 36 video
Tayangan Video September 2025: 182.814 views
Waktu Tayang Video September 2025: 10.179 jam
Penambahan Subscribers September 2025: +1.789
Channel YouTube YUFID KIDS
Total Video Yufid Edu: 3.087 video
Total Subscribers: 331.751
Total Tayangan Video: 22.790.706 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 21 video
Produksi Video September 2025: 36 video
Tayangan Video September 2025: 182.814 views
Waktu Tayang Video September 2025: 10.179 jam
Penambahan Subscribers September 2025: +1.789
Channel YouTube YUFID KIDS
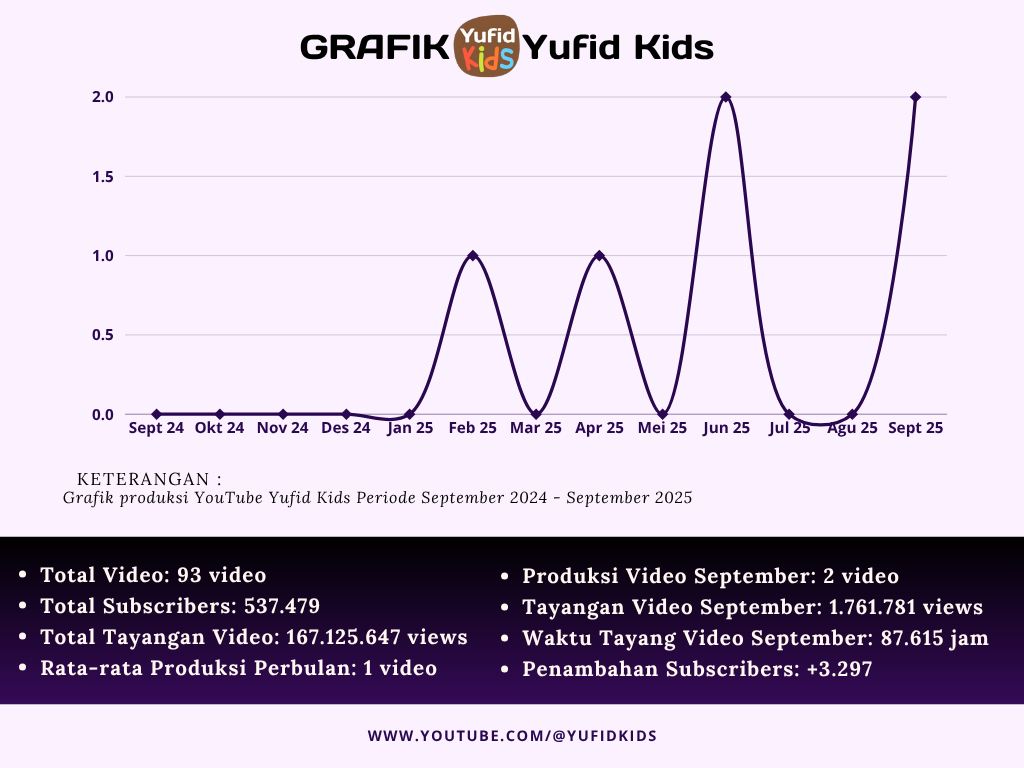 Total Video Yufid Kids: 93 video
Total Subscribers: 537.479
Total Tayangan Video: 167.125.647 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 1 video
Produksi Video September 2025: 2 video
Tayangan Video September 2025: 1.761.781 views
Waktu Tayang Video September 2025: 87.615 jam
Penambahan Subscribers September 2025: +3.297
Untuk memproduksi video Yufid Kids membutuhkan waktu yang lebih panjang dan pekerjaan yang lebih kompleks, namun sejak awal produksi hingga video dipublikasikan tim tetap bekerja setiap harinya.
Channel YouTube Dunia Mengaji
Channel Dunia Mengaji adalah untuk menampung video-video yang secara kualitas pengambilan gambar dan kualitas gambar jauh di bawah standar Yufid.TV, agar konten dakwah tetap bisa dinikmati oleh pemirsa.
Total Video: 272
Total Subscribers: 5.001
Total Tayangan Video: 478.097 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 3 video
Tayangan Video September 2025: 898 views
Jam Tayang Video September 2025: 153 Jam
Penambahan Subscribers September 2025: 7
Channel YouTube العلم نور
Channel “Al-’Ilmu Nuurun” ini merupakan wadah yang berisi ceramah singkat maupun kajian-kajian panjang dari Masyayikh dari Timur Tengah seperti Syaikh Sulaiman Ar-Ruhayli, Syaikh Utsman Al-Khomis, Syaikh Abdurrazaq bin Abdulmuhsin Al Badr hafidzahumullah dan masih banyak yang lainnya yang full menggunakan bahasa Arab. Cocok disimak para pemirsa Yufid.TV yang sudah menguasai bahasa Arab serta ingin belajar bersama guru-guru kita para alim ulama dari Saudi dan sekitarnya.
Total Video: 612
Total Subscribers: 57.200
Total Tayangan Video: 3.443.157 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 8 video
Produksi Video September 2025: 0 video
Tayangan Video September 2025: 32.464 views
Penambahan Subscribers September 2025: +300
Instagram Yufid TV & Instagram Yufid Network
Total Video Yufid Kids: 93 video
Total Subscribers: 537.479
Total Tayangan Video: 167.125.647 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 1 video
Produksi Video September 2025: 2 video
Tayangan Video September 2025: 1.761.781 views
Waktu Tayang Video September 2025: 87.615 jam
Penambahan Subscribers September 2025: +3.297
Untuk memproduksi video Yufid Kids membutuhkan waktu yang lebih panjang dan pekerjaan yang lebih kompleks, namun sejak awal produksi hingga video dipublikasikan tim tetap bekerja setiap harinya.
Channel YouTube Dunia Mengaji
Channel Dunia Mengaji adalah untuk menampung video-video yang secara kualitas pengambilan gambar dan kualitas gambar jauh di bawah standar Yufid.TV, agar konten dakwah tetap bisa dinikmati oleh pemirsa.
Total Video: 272
Total Subscribers: 5.001
Total Tayangan Video: 478.097 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 3 video
Tayangan Video September 2025: 898 views
Jam Tayang Video September 2025: 153 Jam
Penambahan Subscribers September 2025: 7
Channel YouTube العلم نور
Channel “Al-’Ilmu Nuurun” ini merupakan wadah yang berisi ceramah singkat maupun kajian-kajian panjang dari Masyayikh dari Timur Tengah seperti Syaikh Sulaiman Ar-Ruhayli, Syaikh Utsman Al-Khomis, Syaikh Abdurrazaq bin Abdulmuhsin Al Badr hafidzahumullah dan masih banyak yang lainnya yang full menggunakan bahasa Arab. Cocok disimak para pemirsa Yufid.TV yang sudah menguasai bahasa Arab serta ingin belajar bersama guru-guru kita para alim ulama dari Saudi dan sekitarnya.
Total Video: 612
Total Subscribers: 57.200
Total Tayangan Video: 3.443.157 views
Rata-rata Produksi Per Bulan: 8 video
Produksi Video September 2025: 0 video
Tayangan Video September 2025: 32.464 views
Penambahan Subscribers September 2025: +300
Instagram Yufid TV & Instagram Yufid Network
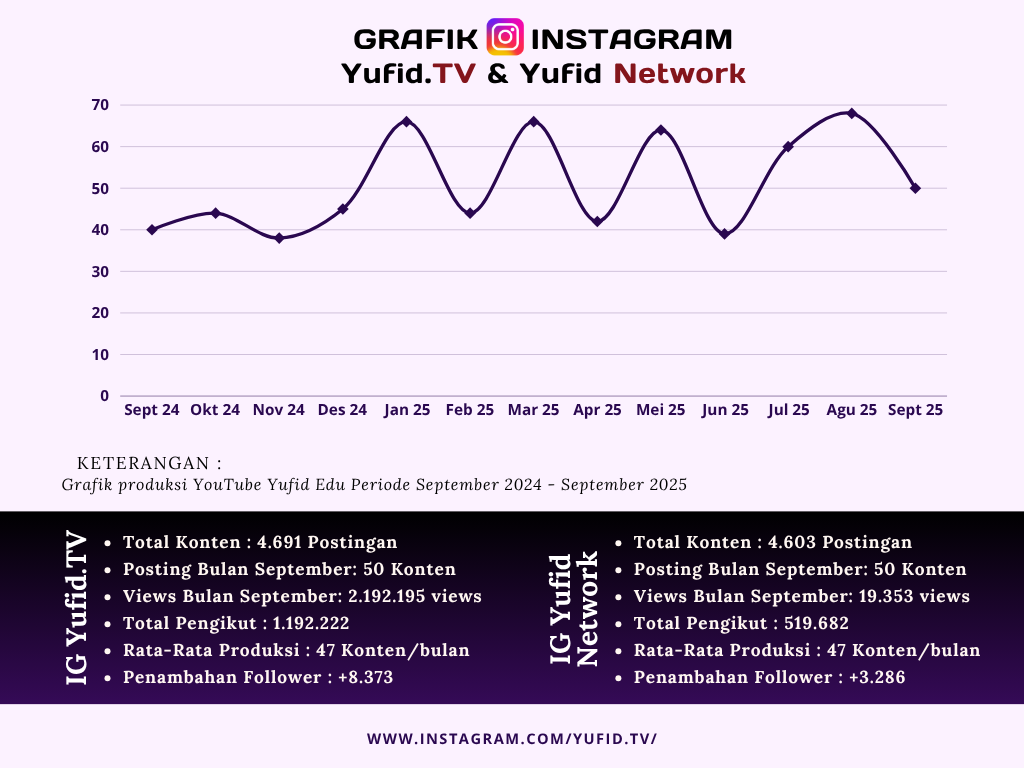 Instagram Yufid.TV
Total Konten: 4.691 Postingan
Total Pengikut: 1.192.222 followers
Konten Bulan September 2025: 50
Views Konten September: 2.192.195 views
Rata-Rata Produksi: 47 konten/bulan
Penambahan Followers September 2025: +8.373
Instagram Yufid Network
Total Konten: 4.603 Postingan
Total Pengikut: 519.682
Konten Bulan September 2025: 50
Views Konten September: 19.353 views
Rata-Rata Produksi: 47 konten/bulan
Penambahan Followers September 2025: +3.286
Pertama kali Yufid memanfaatkan media instagram memiliki nama Yufid Network yaitu sejak tahun 2013, sebelum akhirnya di buatlah akun Yufid.TV pada tahun 2015 agar lebih dikenal seiring dengan berkembangnya channel YouTube Yufid.TV.
Video Nasehat Ulama
Salah satu project yang dikerjakan oleh tim Yufid.TV yaitu video Nasehat Ulama. Video pendek namun penuh dengan faedah berisi penggalan-penggalan nasehat serta jawaban dari pertanyaan kaum muslimin yang disampaikan ulama-ulama terkemuka.
Instagram Yufid.TV
Total Konten: 4.691 Postingan
Total Pengikut: 1.192.222 followers
Konten Bulan September 2025: 50
Views Konten September: 2.192.195 views
Rata-Rata Produksi: 47 konten/bulan
Penambahan Followers September 2025: +8.373
Instagram Yufid Network
Total Konten: 4.603 Postingan
Total Pengikut: 519.682
Konten Bulan September 2025: 50
Views Konten September: 19.353 views
Rata-Rata Produksi: 47 konten/bulan
Penambahan Followers September 2025: +3.286
Pertama kali Yufid memanfaatkan media instagram memiliki nama Yufid Network yaitu sejak tahun 2013, sebelum akhirnya di buatlah akun Yufid.TV pada tahun 2015 agar lebih dikenal seiring dengan berkembangnya channel YouTube Yufid.TV.
Video Nasehat Ulama
Salah satu project yang dikerjakan oleh tim Yufid.TV yaitu video Nasehat Ulama. Video pendek namun penuh dengan faedah berisi penggalan-penggalan nasehat serta jawaban dari pertanyaan kaum muslimin yang disampaikan ulama-ulama terkemuka.
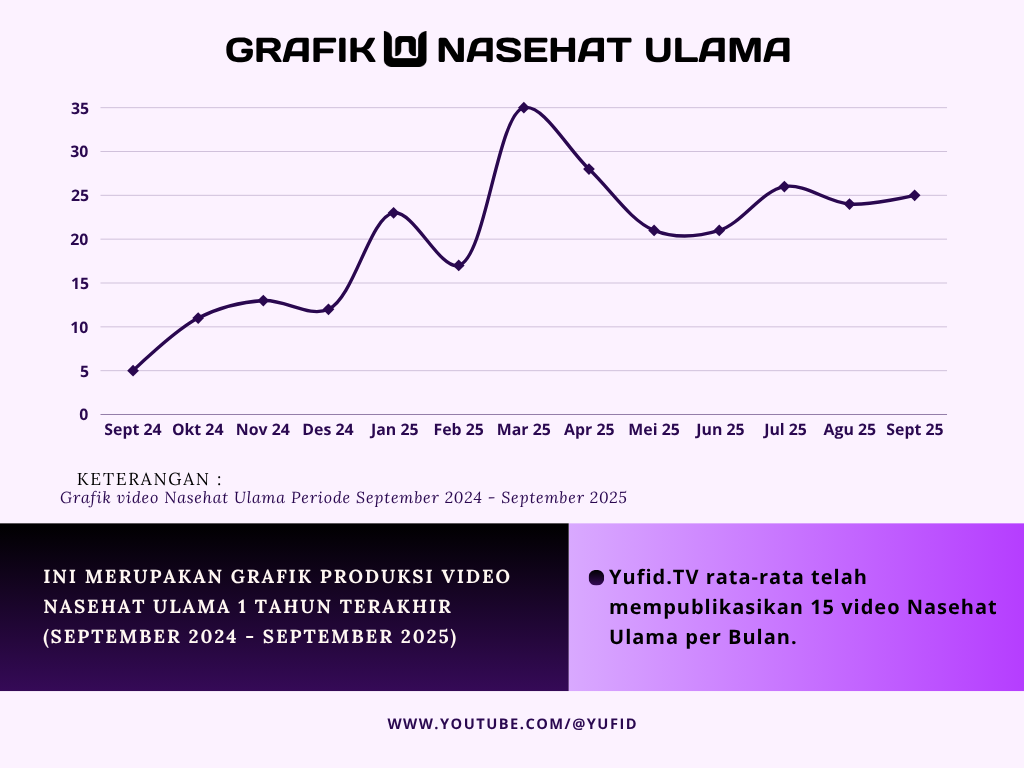 Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, konten Nasehat Ulama di channel YouTube Yufid.TV telah mempublikasikan 25 video.
Nasehat Ulama juga membuat konten baru dengan konsep berbeda dengan tetap mengambil penggalan-penggalan nasehat para masyaikh berbahasa Arab dalam bentuk shorts YouTube dan reels Instagram.
Video Motion Graphic & Yufid Kids
Project unggulan lainnya dari Yufid.TV yaitu pembuatan video animasi motion graphic dan video Yufid Kids. Project motion graphic Yufid.TV memproduksi video-video berkualitas yang memadukan antara pemilihan tema yang tepat berupa potongan-potongan nasehat dari para ustadz atau ceramah-ceramah pendek yang diilustrasikan dalam bentuk animasi yang menarik. Sedangkan video Yufid Kids mengemas materi-materi pendidikan untuk anak yang disajikan dengan gambar animasi anak sehingga membuat anak-anak kita lebih bersemangat dalam mempelajarinya.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, konten Nasehat Ulama di channel YouTube Yufid.TV telah mempublikasikan 25 video.
Nasehat Ulama juga membuat konten baru dengan konsep berbeda dengan tetap mengambil penggalan-penggalan nasehat para masyaikh berbahasa Arab dalam bentuk shorts YouTube dan reels Instagram.
Video Motion Graphic & Yufid Kids
Project unggulan lainnya dari Yufid.TV yaitu pembuatan video animasi motion graphic dan video Yufid Kids. Project motion graphic Yufid.TV memproduksi video-video berkualitas yang memadukan antara pemilihan tema yang tepat berupa potongan-potongan nasehat dari para ustadz atau ceramah-ceramah pendek yang diilustrasikan dalam bentuk animasi yang menarik. Sedangkan video Yufid Kids mengemas materi-materi pendidikan untuk anak yang disajikan dengan gambar animasi anak sehingga membuat anak-anak kita lebih bersemangat dalam mempelajarinya.
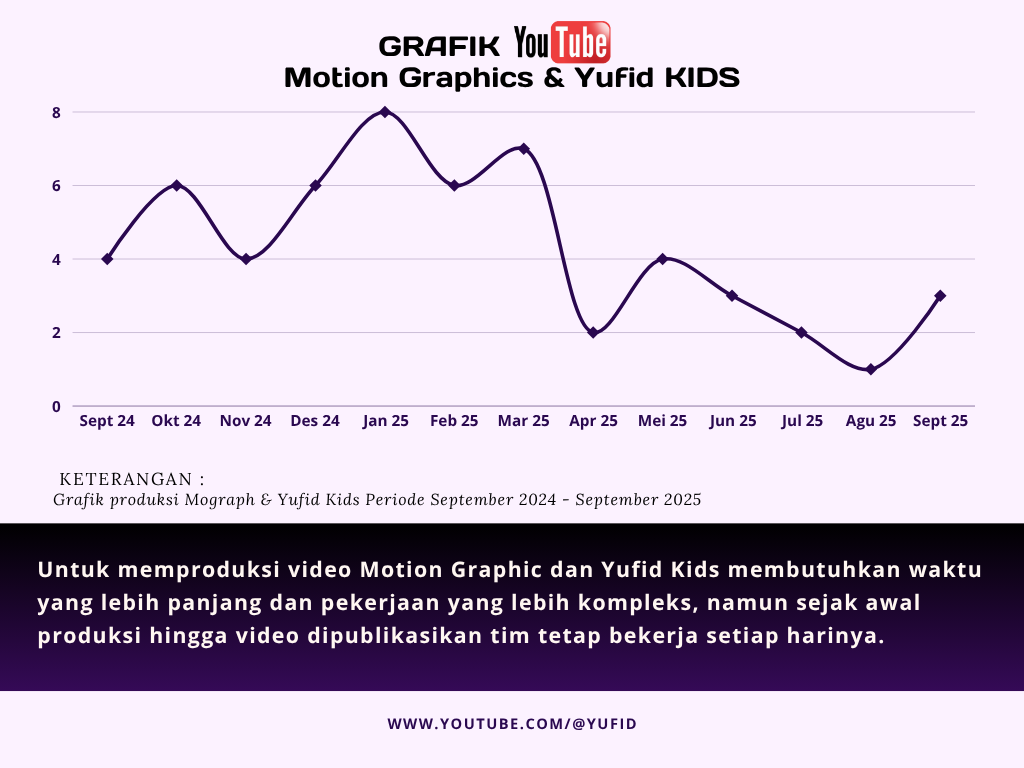 Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, konten Motion Graphics di channel YouTube Yufid.TV telah mempublikasikan 3 video.
Untuk memproduksi video Motion Graphic dan Yufid Kids membutuhkan waktu yang lebih panjang dan pekerjaan yang lebih kompleks, namun sejak awal produksi hingga video dipublikasikan tim tetap bekerja setiap harinya.
Website KonsultasiSyariah.com
KonsultasiSyariah.com merupakan sebuah website yang menyajikan berbagai tanya jawab seputar permasalahan agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kasus dan jawaban dipaparkan secara jelas dan ilmiah, berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta keterangan para ulama. Hingga saat ini, website tersebut telah menuliskan 5.141 artikel yang berisi materi-materi permasalahan agama yang telah dijawab oleh para asatidz. Artikel dalam website KonsultasiSyariah.com juga kami tuangkan ke dalam bentuk audio visual dengan teknik typography dan dibantu oleh pengisi suara (voice over) yang telah memproduksi 2.025 audio dan rata-rata menghasilkan 23 audio per bulan yang siap dimasukkan ke dalam project video Poster Dakwah Yufid.TV.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website KonsultasiSyariah.com telah mempublikasikan 8 artikel.
Website KisahMuslim.com
KisahMuslim.com berisi kumpulan kisah para Nabi dan Rasul, kisah para sahabat Nabi, kisah orang-orang shalih terdahulu, biografi ulama, dan berbagai kisah yang penuh hikmah. Dalam website tersebut sudah ada 1.139 artikel yang banyak kita ambil pelajarannya.
Artikel dalam website KisahMuslim.com juga kami tuangkan ke dalam bentuk Audio Visual dengan teknik typography serta ilustrasi yang menarik dengan dibantu oleh pengisi suara (voice over) yang telah memproduksi 710 audio dan rata-rata menghasilkan 16 audio per bulan yang siap dimasukkan ke dalam project video Kisah Muslim Yufid.TV.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website KisahMuslim.com telah mempublikasikan 3 artikel.
Website KhotbahJumat.com
KhotbahJumat.com berisi materi-materi khutbah yang bisa kita gunakan untuk mengisi khotbah pada ibadah shalat Jumat, terdapat 1.304 artikel hingga saat ini, yang sangat bermanfaat untuk para khatib dan da’i yang mengisi khutbah jumat.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website KhotbahJumat.com telah mempublikasikan 2 artikel.
Website PengusahaMuslim.com
PengusahaMuslim.com merupakan sebuah website yang mengupas seluk beluk dunia usaha dan bisnis guna membantu terbentuknya pengusaha muslim baik secara ekonomi maupun agamanya, yang pada akhirnya menjadi kesatuan kuat dalam memperjuangkan kemaslahatan umat Islam dan memajukan perekonomian Indonesia. Terdapat 2.506 artikel dalam website tersebut yang dapat membantu Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses, tidak hanya di dunia, namun kesuksesan tersebut abadi hingga ke negeri akhirat.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website PengusahaMuslim.com telah mempublikasikan 1 artikel.
*Tim artikel Yufid yang terdiri dari penulis, penerjemah, editor, dan admin website menyiapkan konten untuk seluruh website yang dikelola oleh Yufid secara bergantian.
Website Kajian.net
Kajian.net adalah situs koleksi audio ceramah berbahasa Indonesia terlengkap dari ustadz-ustadz Ahlussunnah wal Jamaah, audio bacaan doa dan hadits berformat mp3, serta software islami dan e-Book kitab-kitab para ulama besar.
Total audio yang tersedia dalam website kajian.net yaitu 34.566 file mp3 dengan total ukuran 487 Gb dan pada bulan September 2025 ini telah mempublikasikan 529 file mp3.
Website Kajian.net bercita-cita sebagai gudang podcast kumpulan audio MP3 ceramah terlengkap yang dapat di download secara gratis dengan harapan dapat memudahkan Anda belajar hukum agama Islam dan aqidah Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafush sholeh. Kami juga rutin mengupload audio MP3 seluruh kajian Yufid ke platform SoundCloud, Anda dapat mengaksesnya melalui https://soundcloud.com/kajiannet, yang pada bulan September 2025 ini saja telah didengarkan 14.837 kali dan telah di download sebanyak 190 file audio.
Project Terjemahan
Project ini bertujuan menerjemahkan konten dakwah, baik itu artikel, buku, dan ceramah para ulama. Konten dakwah yang aslinya berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, konten yang sudah diterjemahkan tersebut diolah kembali menjadi konten video, mp3, e-book, dan artikel di website. Sejak memulai project ini pada tahun 2018, tim penerjemah Yufid telah menerjemahkan 4.489.627 kata dengan rata-rata produksi per bulan 53.447 kata.
Dalam 1 bulan terakhir yaitu bulan September 2025, project terjemahan ini telah menerjemahkan 49.019 kata.
Perekaman Artikel Menjadi Audio
Program ini adalah merekam seluruh artikel yang dipublikasikan di website-website Yufid seperti KonsultasiSyariah.com, PengusahaMuslim.com dan KisahMuslim.com ke dalam bentuk audio. Program ini bertujuan untuk memudahkan kaum muslimin mengakses konten dakwah dalam bentuk audio, terutama bagi mereka yang sibuk sehingga tidak ada kesempatan untuk membaca artikel. Mereka dapat mendengarkan audio yang sudah Yufid rekam sambil mereka beraktivitas, semisal di kendaraan, sambil bekerja, berolahraga, dan lain-lain.
Total artikel yang sudah direkam dalam format audio sejak pertama dimulai program ini tahun 2017 yaitu 2.761 artikel dengan total durasi audio 262 jam dengan rata-rata perekaman 28 artikel per bulan.
Dalam 1 bulan terakhir yaitu bulan September 2025, perekaman audio yang telah diproduksi yaitu 18 artikel.
Pengelolaan Server
Yufid mengelola tujuh server yang di dalamnya berisi website-website dakwah, ada server khusus untuk website Yufid, website yang telah dijelaskan pada point-point diatas hanya sebagian kecil dari website yang kami kelola, yaitu bertotal 29 website dalam satu server tersebut. Selain itu terdapat juga website para ulama yang diletakkan di server yang berbeda dari server Yufid, ada pula website-website dakwah, streaming radio dll. Dari ketujuh server yang Yufid kelola kurang lebih terdapat 107 website yang masih aktif hingga saat ini.
Demikian telah kami sampaikan laporan produksi Yufid Network pada bulan September 2025.
Wallahu a’lam… Washallallahu ‘ala Nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa sahbihi ajma’in, walhamdulillahi rabbil ‘alamin.
🔍 Cara Menghadiahkan Al Fatihah, Istri Yang Sabar, Pertanyaan Tauhid, Haid Sebulan 2x
Visited 29 times, 1 visit(s) today
Post Views: 323
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, konten Motion Graphics di channel YouTube Yufid.TV telah mempublikasikan 3 video.
Untuk memproduksi video Motion Graphic dan Yufid Kids membutuhkan waktu yang lebih panjang dan pekerjaan yang lebih kompleks, namun sejak awal produksi hingga video dipublikasikan tim tetap bekerja setiap harinya.
Website KonsultasiSyariah.com
KonsultasiSyariah.com merupakan sebuah website yang menyajikan berbagai tanya jawab seputar permasalahan agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kasus dan jawaban dipaparkan secara jelas dan ilmiah, berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta keterangan para ulama. Hingga saat ini, website tersebut telah menuliskan 5.141 artikel yang berisi materi-materi permasalahan agama yang telah dijawab oleh para asatidz. Artikel dalam website KonsultasiSyariah.com juga kami tuangkan ke dalam bentuk audio visual dengan teknik typography dan dibantu oleh pengisi suara (voice over) yang telah memproduksi 2.025 audio dan rata-rata menghasilkan 23 audio per bulan yang siap dimasukkan ke dalam project video Poster Dakwah Yufid.TV.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website KonsultasiSyariah.com telah mempublikasikan 8 artikel.
Website KisahMuslim.com
KisahMuslim.com berisi kumpulan kisah para Nabi dan Rasul, kisah para sahabat Nabi, kisah orang-orang shalih terdahulu, biografi ulama, dan berbagai kisah yang penuh hikmah. Dalam website tersebut sudah ada 1.139 artikel yang banyak kita ambil pelajarannya.
Artikel dalam website KisahMuslim.com juga kami tuangkan ke dalam bentuk Audio Visual dengan teknik typography serta ilustrasi yang menarik dengan dibantu oleh pengisi suara (voice over) yang telah memproduksi 710 audio dan rata-rata menghasilkan 16 audio per bulan yang siap dimasukkan ke dalam project video Kisah Muslim Yufid.TV.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website KisahMuslim.com telah mempublikasikan 3 artikel.
Website KhotbahJumat.com
KhotbahJumat.com berisi materi-materi khutbah yang bisa kita gunakan untuk mengisi khotbah pada ibadah shalat Jumat, terdapat 1.304 artikel hingga saat ini, yang sangat bermanfaat untuk para khatib dan da’i yang mengisi khutbah jumat.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website KhotbahJumat.com telah mempublikasikan 2 artikel.
Website PengusahaMuslim.com
PengusahaMuslim.com merupakan sebuah website yang mengupas seluk beluk dunia usaha dan bisnis guna membantu terbentuknya pengusaha muslim baik secara ekonomi maupun agamanya, yang pada akhirnya menjadi kesatuan kuat dalam memperjuangkan kemaslahatan umat Islam dan memajukan perekonomian Indonesia. Terdapat 2.506 artikel dalam website tersebut yang dapat membantu Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses, tidak hanya di dunia, namun kesuksesan tersebut abadi hingga ke negeri akhirat.
Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website PengusahaMuslim.com telah mempublikasikan 1 artikel.
*Tim artikel Yufid yang terdiri dari penulis, penerjemah, editor, dan admin website menyiapkan konten untuk seluruh website yang dikelola oleh Yufid secara bergantian.
Website Kajian.net
Kajian.net adalah situs koleksi audio ceramah berbahasa Indonesia terlengkap dari ustadz-ustadz Ahlussunnah wal Jamaah, audio bacaan doa dan hadits berformat mp3, serta software islami dan e-Book kitab-kitab para ulama besar.
Total audio yang tersedia dalam website kajian.net yaitu 34.566 file mp3 dengan total ukuran 487 Gb dan pada bulan September 2025 ini telah mempublikasikan 529 file mp3.
Website Kajian.net bercita-cita sebagai gudang podcast kumpulan audio MP3 ceramah terlengkap yang dapat di download secara gratis dengan harapan dapat memudahkan Anda belajar hukum agama Islam dan aqidah Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafush sholeh. Kami juga rutin mengupload audio MP3 seluruh kajian Yufid ke platform SoundCloud, Anda dapat mengaksesnya melalui https://soundcloud.com/kajiannet, yang pada bulan September 2025 ini saja telah didengarkan 14.837 kali dan telah di download sebanyak 190 file audio.
Project Terjemahan
Project ini bertujuan menerjemahkan konten dakwah, baik itu artikel, buku, dan ceramah para ulama. Konten dakwah yang aslinya berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, konten yang sudah diterjemahkan tersebut diolah kembali menjadi konten video, mp3, e-book, dan artikel di website. Sejak memulai project ini pada tahun 2018, tim penerjemah Yufid telah menerjemahkan 4.489.627 kata dengan rata-rata produksi per bulan 53.447 kata.
Dalam 1 bulan terakhir yaitu bulan September 2025, project terjemahan ini telah menerjemahkan 49.019 kata.
Perekaman Artikel Menjadi Audio
Program ini adalah merekam seluruh artikel yang dipublikasikan di website-website Yufid seperti KonsultasiSyariah.com, PengusahaMuslim.com dan KisahMuslim.com ke dalam bentuk audio. Program ini bertujuan untuk memudahkan kaum muslimin mengakses konten dakwah dalam bentuk audio, terutama bagi mereka yang sibuk sehingga tidak ada kesempatan untuk membaca artikel. Mereka dapat mendengarkan audio yang sudah Yufid rekam sambil mereka beraktivitas, semisal di kendaraan, sambil bekerja, berolahraga, dan lain-lain.
Total artikel yang sudah direkam dalam format audio sejak pertama dimulai program ini tahun 2017 yaitu 2.761 artikel dengan total durasi audio 262 jam dengan rata-rata perekaman 28 artikel per bulan.
Dalam 1 bulan terakhir yaitu bulan September 2025, perekaman audio yang telah diproduksi yaitu 18 artikel.
Pengelolaan Server
Yufid mengelola tujuh server yang di dalamnya berisi website-website dakwah, ada server khusus untuk website Yufid, website yang telah dijelaskan pada point-point diatas hanya sebagian kecil dari website yang kami kelola, yaitu bertotal 29 website dalam satu server tersebut. Selain itu terdapat juga website para ulama yang diletakkan di server yang berbeda dari server Yufid, ada pula website-website dakwah, streaming radio dll. Dari ketujuh server yang Yufid kelola kurang lebih terdapat 107 website yang masih aktif hingga saat ini.
Demikian telah kami sampaikan laporan produksi Yufid Network pada bulan September 2025.
Wallahu a’lam… Washallallahu ‘ala Nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa sahbihi ajma’in, walhamdulillahi rabbil ‘alamin.
🔍 Cara Menghadiahkan Al Fatihah, Istri Yang Sabar, Pertanyaan Tauhid, Haid Sebulan 2x
Visited 29 times, 1 visit(s) today
Post Views: 323